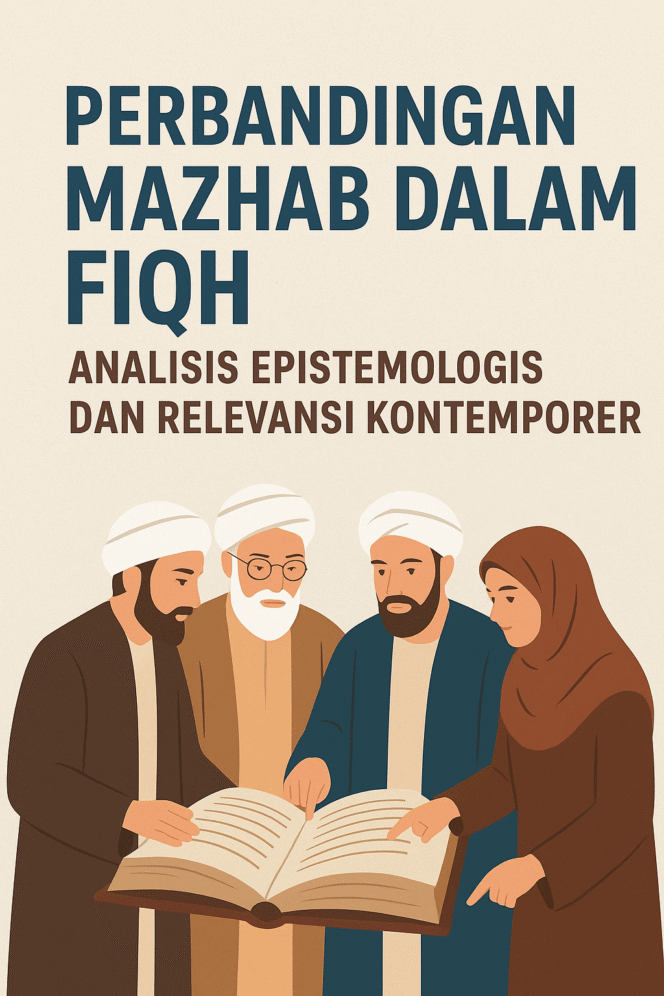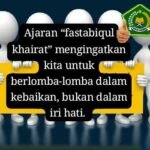Abstrak
Email: kangdianrahmat@gmail.com
Artikel ini membahas studi perbandingan mazhab dalam fiqh Islam dengan menekankan aspek epistemologis, metodologis, dan urgensinya dalam menjawab problematika hukum kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research*, penelitian ini mengkaji alasan terjadinya perbedaan mazhab, respon ulama klasik dan kontemporer terhadap fenomena taqlid, tarjih, serta ijtihad, dan implikasinya bagi pengembangan hukum Islam modern. Data diperoleh dari literatur klasik (kitab fiqh, ushul fiqh, dan syarah hadis) serta literatur akademik mutakhir dari jurnal terindeks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mazhab muncul karena faktor linguistik, metodologi penilaian hadis, perbedaan kaidah ushul, qiyas, serta penggunaan dalil ikhtilaf seperti istihsan* dan *maslahah mursalah*. Kajian ini menegaskan urgensi pendekatan muqaranah fiqh (perbandingan fiqh) untuk menghindari fanatisme mazhab, sekaligus mendorong lahirnya ijtihad kontemporer yang kontekstual dengan maqasid syariah.
Kata kunci ; Fiqh, Perbandingan Mazhab, Ijtihad, Maqasid Syariah, Tarjih
A. Pendahuluan
Studi perbandingan mazhab merupakan salah satu disiplin penting dalam khazanah fiqh Islam. Tujuannya bukan hanya untuk menampilkan ragam pendapat para imam mazhab, tetapi juga untuk menemukan landasan epistemologis dari setiap perbedaan hukum. Dalam sejarahnya, perbandingan mazhab sering diperdebatkan, sebagian ulama memandangnya sebagai sarana ilmiah untuk memperkaya khazanah hukum, sementara sebagian lain khawatir dapat menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum (Al-Jabiri, 2014; Kamali, 2003).
Fenomena taqlid yang menguat pada masa ulama mutaakhkhirin melahirkan stagnasi hukum Islam, sementara semangat ijtihad yang digagas ulama kontemporer seperti Yassir Auda (2008) dengan *maqasid approach* membuka ruang untuk memperbarui fiqh agar relevan dengan dinamika sosial modern. Artikel ini mencoba mengkaji perbandingan mazhab secara akademik, mengidentifikasi faktor penyebab perbedaan pendapat, sekaligus menganalisis relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer.
B. Kajian Pustaka
- Perbedaan Mazhab: Ibn Khaldun menjelaskan bahwa perbedaan mazhab merupakan konsekuensi metodologi ijtihad yang berbeda dalam memahami dalil syar‘i, baik dari aspek bahasa, riwayat hadis, maupun kaidah ushul.
- Taqlid vs Ijtihad**: Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam mengkritik taqlid buta karena menutup pintu ijtihad. Imam Syafi‘i bahkan melarang pengikutnya untuk bertaklid penuh tanpa verifikasi dalil.
- Pendekatan Kontemporer**: Yassir Auda melalui teori sistem *maqasid syariah* menegaskan perlunya membaca fiqh dengan prinsip *al-ma‘alāt* (konsekuensi), *al-maqāsid* (tujuan), dan *al-muwazanah* (pertimbangan maslahat).
C. Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan metode library research dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan dari:
- Literatur klasik: karya fiqh empat mazhab, ushul fiqh, dan komentar ulama.
- Literatur kontemporer: jurnal-jurnal Scopus terkait hukum Islam, maqasid syariah, dan teori hukum.
Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan pendapat para ulama, kemudian menganalisis perbedaannya untuk menemukan relevansi dengan konteks hukum Islam saat ini.
D. Pembahasan
Faktor Penyebab Perbedaan Mazhab
Berdasarkan literatur klasik, perbedaan mazhab disebabkan oleh enam faktor utama: (a) perbedaan linguistik dalam memahami lafaz Al-Qur’an dan hadis, (b) perbedaan otoritas riwayat hadis, (c) perbedaan kaidah ushul fiqh, (d) perbedaan dalam menilai dalil nasakh dan tarjih, (e) perbedaan dalam penerimaan qiyas, dan (f) penggunaan dalil istihsan, maslahah mursalah, dan istidlal.
Sikap Ulama terhadap Perbandingan Mazhab
Ulama mutaakhkhirin banyak yang menolak praktik muqaranah karena dianggap dapat menimbulkan kebingungan hukum. Namun, tokoh seperti Imam Abu Syamah dan Syekh al-Maraghi menekankan pentingnya membandingkan mazhab demi menemukan dalil yang lebih kuat dan relevan, bahkan membuka pintu ijtihad untuk memperbaharui hukum Islam.
Dalil Naqli tentang Perbedaan
Al-Qur’an sendiri telah memberi isyarat tentang adanya perbedaan hukum. Allah berfirman: *“…Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”* (Q.S. An-Nahl: 43). Ayat ini menjadi dasar bahwa umat diperintahkan untuk merujuk kepada ulama, meskipun mereka berbeda pendapat. Demikian pula hadis Nabi: *“Ikhtilafu ummati rahmah”* (perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat), menunjukkan bahwa perbedaan ijtihad justru menjadi rahmat yang memperkaya khazanah hukum Islam.
Dalil Naqli tentang Ijtihad
Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Mu‘adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman menjadi landasan kuat ijtihad. Nabi bertanya: “Dengan apa engkau akan memutuskan hukum?” Mu‘adz menjawab: “Dengan Kitab Allah.” Nabi bertanya lagi: “Jika tidak ada dalam Kitab Allah?” Ia menjawab: “Dengan sunnah Rasulullah.” Nabi bertanya lagi: “Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah?” Ia menjawab: “Aku akan berijtihad dengan pendapatku.” Nabi kemudian menepuk dadanya seraya berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik utusan Rasulullah kepada sesuatu yang diridai Rasulullah.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi). Hadis ini menegaskan legitimasi ijtihad sebagai bagian dari dinamika hukum Islam.
Integrasi Teori Hukum Alam dan Positivisme Hukum
Dalam kerangka teori hukum, perbedaan mazhab dapat dianalisis melalui dikotomi *natural law theory* (hukum alam) dan *legal positivism*. Teori hukum alam menekankan keadilan sebagai nilai moral, sementara positivisme hukum menegaskan hukum sebagai produk otoritas. Dalam fiqh, mazhab adalah representasi hukum alam berbasis wahyu, tetapi ketika diformalisasi menjadi hukum negara, ia memasuki ranah positivisme hukum (Hart, 1994). Dialektika ini menunjukkan keseimbangan antara nilai transendental dan kebutuhan praktis hukum.
Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman
Lawrence Friedman (1975) membagi sistem hukum menjadi struktur, substansi, dan kultur. Dalam perbandingan mazhab, struktur hukum adalah otoritas syariah, substansi adalah produk fiqh, sedangkan kultur hukum adalah praktik masyarakat. Muqaranah fiqh relevan karena menjembatani ketiganya, sehingga hukum Islam tetap adaptif dalam menghadapi dinamika sosial.
Teori Living Law Eugen Ehrlich
Menurut Ehrlich (1936), hukum yang hidup adalah hukum yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Dalam fiqh, fenomena *talfiq* dan praktik masyarakat yang tidak selalu sesuai dengan satu mazhab tertentu membuktikan bahwa hukum Islam berfungsi sebagai *living law* yang fleksibel.
Relevansi dengan Maqasid Syariah Kontemporer
Yassir Auda (2008) menegaskan pentingnya pendekatan maqasid dalam membaca fiqh. Dengan menggabungkan hukum alam (keadilan moral), positivisme (kepastian hukum), sistem hukum (struktur, substansi, kultur), dan *living law* (kebiasaan masyarakat), maka perbandingan mazhab dapat menjadi metode rekonstruksi hukum Islam yang komprehensif dan relevan.
Analisis
Pertama, jika dilihat dengan kacamata **teori sistem hukum Friedman**, maka perbedaan mazhab mencerminkan dinamika *substansi hukum* yang kaya. Substansi hukum di sini adalah ragam fatwa, kaidah, dan hasil ijtihad para imam. Namun, substansi tersebut tidak akan berarti jika tidak dihubungkan dengan *struktur hukum* (otoritas lembaga, pengadilan, dan ulama) serta *kultur hukum* (tradisi masyarakat). Banyak kasus menunjukkan bahwa perbedaan mazhab menjadi masalah ketika hanya dipandang dari sisi substansi semata. Namun, ketika ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang lebih luas, perbedaan itu justru memperkaya struktur hukum dan memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih sesuai dengan kultur mereka. Dengan kata lain, muqaranah fiqh adalah mekanisme sistem hukum Islam agar tetap hidup, adaptif, dan kontekstual.
Kedua, dalam perspektif **maqasid syariah**, perbedaan mazhab dapat dianalisis dari sisi tujuan hukum (maqasid) dibanding sekadar perbedaan teks. Misalnya, perbedaan dalam masalah wudu antara mazhab Hanafi, Syafi‘i, dan Maliki bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan mencerminkan upaya menjaga kebersihan, kesucian, dan kesiapan spiritual sebelum shalat. Jika dilihat dari maqasid, maka tujuan yang dicapai tetap sama meski bentuk aplikasinya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman mazhab sejatinya bukan kontradiksi, melainkan pluralitas cara untuk mencapai maqasid yang satu.
Ketiga, analisis integratif dengan teori sistem hukum dan maqasid syariah memperlihatkan bahwa perbedaan mazhab tidak boleh dimaknai sebagai hambatan, melainkan peluang untuk melahirkan *ijtihad jama‘i* (kolektif) yang lebih komprehensif. Sistem hukum menekankan bahwa setiap produk fiqh harus berfungsi dalam struktur dan kultur masyarakat, sedangkan maqasid menekankan nilai universal seperti keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan rahmat (*rahmah*). Jika dua kerangka ini digabungkan, maka hukum Islam tidak akan terjebak pada fanatisme mazhab atau formalisme hukum negara, melainkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern secara dinamis. Dengan cara ini, perbandingan mazhab menjadi instrumen penting bagi rekonstruksi hukum Islam yang progresif.
E. Kesimpulan
Perbandingan mazhab merupakan sarana ilmiah untuk memahami dinamika hukum Islam. Perbedaan mazhab tidak semestinya menjadi sumber perpecahan, melainkan kekayaan intelektual yang menegaskan pluralitas ijtihad. Dengan penguatan dalil naqli, teori hukum modern, serta maqasid syariah, studi ini menegaskan urgensi muqaranah fiqh untuk menghindari fanatisme mazhab dan merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
F.Daftar Pustaka
Auda, Y. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Friedman, L. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.
Ibn Khaldun. (2005). *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr.
Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
Al-Jabiri, M. A. (2014). *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah.
Syafe‘i, R. (2014). *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia (UIN Bandung).
Qodir, Z. (2020). “Ijtihad Kontemporer dalam Bingkai Maqasid Syariah.” *Jurnal Ilmu Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 19(2), 201–220.
.