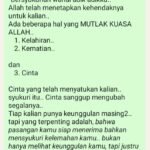Ada begitu banyak tulisan yang telah mengulas masalah nikah siri. Dari sekian banyak tulisan tersebut, mayoritasnya menyasar pada perempuan dan hak-haknya yang terabaikan. Hanya sedikit yang menyinggung dampaknya terhadap anak. Padahal dua-duanya sama-sama menjadi ‘korban’.
Dari sedikit yang penulis temukan, topik yang dibicarakan adalah hilangnya hubungan keperdataan anak dari bapak kandungnya. Akibatnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
Berbeda dari topik sebelumnya, dalam tulisan ini penulis hendak memberikan ulasan terkait dampak nikah siri bagi status perwalian anak. Secara spesifik, masalah yang dibicarakan dipersempit pada kasus nikah siri yang diikuti dengan kawin hamil. Signifikansi dari tulisan ini adalah menjelaskan kerancuan status perwalian akibat nikah siri yang diikuti kawin hamil.
Perspektif yang digunakan adalah kepenghuluan. Perspektif ini dianggap penting mengingat penghulu sebagai pelaksana kebijakan dari regulasi yang beririsan langsung dengan masalah nikah siri dan kawin hamil. Selain itu, pengambilan kebijakan di lapangan praktiknya juga turut melibatkan ‘ijtihad’ dari penghulu.
Nikah Siri dan Kawin Hamil
Nikah siri dalam tulisan ini sebagaimana dijelaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), menurut agama Islam sudah sah. Definisi ini relevan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Tetapi meski definisinya menyebutkan demikian, perlu dicatat bahwa praktiknya di lapangan sering kali ditemukan cacat dalam pemenuhan rukun nikahnya, terutama wali. Banyak kasus yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa para pelaku nikah siri tidak memahami ketentuan wali, baik dari ragam hingga tertib urutannya. Hingga tak jarang menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya.
Sementara kawin hamil yang dikehendaki dalam tulisan ini sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII Pasal 53 ayat 1 adalah “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.
Dari dua definisi ini, masalah yang hendak diulas dapat digambarkan dengan pasangan yang telah melakukan nikah siri kemudian melakukan hubungan suami-istri dan hamil lalu mengajukan pencatatan nikah di KUA melalui mekanisme nikah resmi.
Praktik yang tersaji di lapangan sebenarnya sangat bervariasi dipandang dari jarak pelaksanaan kawin hamil (baca: nikah tercatat) dan kelahirannya. Namun secara umum, praktiknya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: kurang dan lebih dari enam bulan. Pengelompokan ini didasarkan pada waktu enam bulan batas minimal usia kehamilan.
Aspek yang dijadikan pertimbangan selain batas waktu minimal sebelumnya adalah pertama status legalitas nikah siri, diakui dan tidaknya. Meski secara hukum positif tidak diakui, keberadaan nikah siri tidak menjadi hilang begitu saja. Banyak juga kasus yang oleh Pengadilan Agama ditetapkan legalitasnya.
Kedua, dualisme mazhab penghulu dalam merespons masalah kawin hamil. Untuk yang satu ini, pembaca dapat membaca ulasan lengkapnya pada Dominasi Fikih Syafii dan Perilaku ‘Mendua’ pada Kawin Hamil. Intinya bahwa penghulu belum menerapkan KHI secara konsisten serta cenderung subjektif pada mazhab yang ia anut.
Rancunya Status Wali
Kewalian merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan nasab. Itu sebabnya, pada bahasan sebelumnya dasar yang digunakan adalah batas waktu minimal kehamilan. Karena dengannya, hubungan nasab ditetapkan. Di sisi lain, pencatatan pernikahan di Indonesia mengacu pada dokumen pendaftaran nikah yang artinya perhitungan waktu enam bulan dihitung dari tanggal pernikahan resmi.
Dari sini, nikah siri dan kawin hamil menemukan masalahnya. Kehamilan dari nikah siri sering kali menimbulkan tanda tanya karena tidak genap sembilan bulan merujuk pada lama waktu kehamilan normal. Kemungkinannya bisa kurang atau lebih dari enam bulan. Meskipun arah penetapan keduanya sama-sama berujung pada wali hakim (Kepala KUA) dan bukan wali nasab, pertimbangannya sedikit berbeda.
Jika kurang dari enam bulan penetapan wali hakim dikarenakan nihilnya dokumen administratif. Sementara jika lebih dari enam bulan, beranikah kita menetapkan keabsahan nikah siri yang telah dilakukan lampau padahal tidak ditemukan bukti pendukung sama sekali, kecuali ikrar atau pengakuan. Yang dalam bahasan sebelumnya sempat disinggung banyaknya kasus nikah siri yang tidak memenuhi rukun. Padahal realitas sebenarnya, bisa jadi nikah siri yang dilakukan lampau tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Meskipun jika mengacu pada KHI Pasal 99, masalah nikah siri dan kawin hamil ini sebenarnya dapat dianggap selesai karena Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sehingga anak yang lahir dalam masalah kawin hamil memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, terlepas asal-usulnya dari nikah siri yang sah atau tidak atau bahkan pembuahan di luar nikah.
Selain itu Wahbah al-Zuhaili juga telah memberikan penjelasan yang bijak terkait dengan hal ini,
يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا الإقرار بالولد يثبت به نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشبهة، حملاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض.
Para ulama bersepakat bahwa diperbolehkan bagi pasangan yang telah berzina untuk menikah. Jika kandungannya lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan maka memiliki hubungan nasab. Jika tidak, maka tidak memiliki hubungan nasab, kecuali ayah biologisnya mengakui (ikrar) bahwa anak tersebut berasal darinya (tidak dari zina). Ikrar ini dapat menetapkan hubungan nasab karena dimungkinkan adanya pernikahan yang telah ia lakukan sebelumnya atau hubungan yang syubhat berdasar asas kesalehan dan perlindungan harga diri seseorang (Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh: 9, 6648)
Namun demikian banyak penghulu yang ‘tidak berani’ mengikuti pendapat ini dan cenderung pada subjektif mazhab yang ia ikuti, mayoritas Syafii, hingga berujung pada rancunya wali nikah akibat nikah siri. Penulis tidak menyalahkan penghulu atas ijtihad yang dilakukan. Justru penulis hendak menunjukkan betapa nikah siri telah menghadirkan kerumitan administrasi bagi penghulu di era modern ini. Karenanya, meski halal secara syariat, hukum nikah siri adalah haram karena menimbulkan bahaya administrasi. Wallahu a‘lam bi al-shawab. []