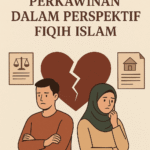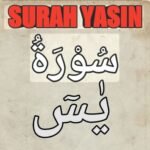Berbicara tentang penghulu pada masa kolonial berarti mengulas satu bab penting dalam sejarah sosial keagamaan di Nusantara. Sosok penghulu menjadi figur yang unik, di satu sisi mewakili otoritas agama Islam, di sisi lain harus tunduk pada sistem kekuasaan kolonial Belanda yang berupaya mengontrol kehidupan masyarakat pribumi. Kiprah mereka menggambarkan tarik-menarik antara adat, agama, dan kekuasaan yang berlangsung sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Peran Awal Penghulu di Tengah Kolonialisme
Pada awal masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa kekuatan Islam memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat pribumi. Untuk itu, mereka tidak serta-merta menghapus peran ulama dan penghulu, melainkan berusaha menempatkan keduanya dalam struktur pemerintahan yang bisa diawasi. Dalam sistem ini, penghulu berfungsi sebagai pegawai agama yang diangkat oleh pemerintah kolonial untuk mengurus urusan pernikahan, warisan, dan hukum Islam terbatas.
Namun posisi tersebut tidak sepenuhnya otonom. Penghulu harus bekerja di bawah pengawasan “Asisten Residen” atau pejabat kolonial lainnya. Dengan demikian, penghulu menjadi perantara antara kepentingan rakyat Muslim dengan kepentingan pemerintah kolonial yang sekuler. Di sinilah muncul dilema: bagaimana mempertahankan kemurnian agama di tengah tekanan kekuasaan yang bersifat politik?
Hubungan Penghulu dengan Adat dan Agama
Masyarakat Nusantara saat itu hidup dalam sistem sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh adat istiadat lokal. Penghulu dituntut tidak hanya memahami hukum Islam, tetapi juga mampu menyesuaikannya dengan nilai-nilai adat yang berlaku di daerahnya. Dalam praktiknya, banyak penghulu yang berperan sebagai juru damai, penengah sengketa, dan penasehat adat bagi masyarakat.
Perpaduan antara adat dan agama ini melahirkan bentuk hukum yang khas, yaitu hukum Islam lokal (adat Islam), yang sering kali lebih fleksibel daripada hukum syariat murni. Penghulu menjadi tokoh penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama, tanpa menimbulkan benturan sosial.
Penghulu dalam Struktur Pemerintahan Kolonial
Pada abad ke-19, Belanda membentuk lembaga Priesterraad (Raad Agama) yang berfungsi mengatur urusan keagamaan Islam, terutama dalam hal perkawinan dan warisan. Penghulu ditempatkan sebagai anggota lembaga ini, namun kedudukannya bukan sebagai pemegang otoritas agama bebas, melainkan sebagai pegawai pemerintah yang harus mengikuti aturan kolonial.
Meski demikian, tidak sedikit penghulu yang memanfaatkan posisi tersebut untuk memperkuat eksistensi Islam di wilayahnya. Mereka membangun madrasah, mengembangkan dakwah, serta memperjuangkan hak umat dalam batas-batas yang masih diperbolehkan oleh penguasa kolonial. Dari sini terlihat bahwa penghulu tidak hanya tunduk, tetapi juga melakukan bentuk perlawanan kultural melalui pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan.
Dinamika Kekuasaan dan Moralitas
Kedudukan penghulu di masa kolonial sering kali menimbulkan pandangan ganda di masyarakat. Sebagian menganggap mereka sebagai “abdi pemerintah” yang bekerja demi kepentingan Belanda, bahkan ada yang menyebut penghulu sebagai “Kiai Londo”, namun tidak sedikit pula dari masyarakat yang memandang penghulu sebagai “penjaga moral” yang berusaha melindungi umat dari pengaruh sekularisme kolonial.
Faktanya, banyak penghulu yang menjalankan peran ganda: di siang hari mereka bekerja secara administratif di bawah sistem kolonial, tetapi di luar itu mereka tetap menjadi tokoh panutan keagamaan dan pemimpin spiritual di masyarakat. Dalam kondisi serba terbatas, penghulu menjadi simbol adaptasi dan ketahanan Islam di bawah kekuasaan asing.
Akhir Masa Kolonial dan Lahirnya Kesadaran Baru
Menjelang akhir kekuasaan kolonial, terutama setelah masa pendudukan Jepang, posisi penghulu mulai berubah. Pemerintah kolonial mulai menyadari bahwa lembaga agama memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sosial. Di sisi lain, para penghulu dan ulama juga mulai memiliki kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa.
Banyak penghulu kemudian terlibat dalam gerakan sosial dan pendidikan, termasuk aktif dalam organisasi keagamaan seperti Haji Ichsan dan Muhammad Adnan yang memilih terlibat dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dari sinilah penghulu memasuki babak baru dari “pegawai kolonial” menjadi “pejabat negara” yang berperan dalam sistem pemerintahan Indonesia merdeka.
Kiprah penghulu di masa kolonial memperlihatkan betapa kuatnya daya lentur lembaga keagamaan Islam dalam menghadapi tekanan kekuasaan. Di antara benturan adat, agama, dan politik, penghulu tetap mampu menjalankan fungsi sosial dan spiritualnya bagi masyarakat. Mereka adalah penjaga nilai, penerus tradisi, dan pelaku sejarah yang berperan penting dalam membentuk wajah keislaman di Indonesia.
Referensi:
Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia. Jakarta: Kencana, 2013.
Steenbrink, Karel A. Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
Sumarno, Wisnu Fachrudin dkk. “Pasang Surut Penghulu sebagai Abdi Ndalem di Kasunanan Surakarta 1931–1937 M”. Jurnal Batuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol. 02, No. 01, 2023.
Purbaningrum, Dwi Fariska, dan Kusairi Latif. “Penghulu-Penghulu Keraton di Bidang Agama, Hukum dan Pendidikan di Kasunanan dan Mangkunegaran Tahun 1936–1947”. Journal Historiography: Journal of Indonesian History and Education, Vol. 03, No. 02, 2023.
Abdurrahman, Dudung. Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Ombak, 2012.
Pringgodigdo, A.K. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat, 1980.
Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi, 2008.
Deliar Noer. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942. Jakarta: LP3ES, 1980.
Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.