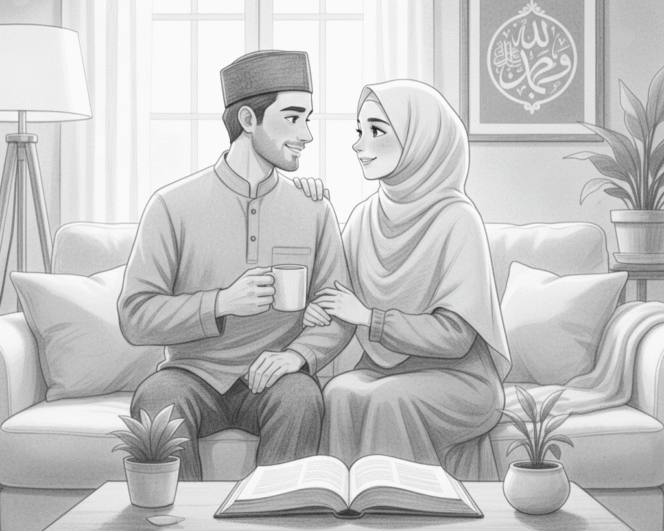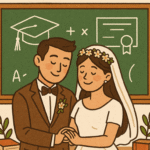Sebagai khadimul ummah—pelayan masyarakat—yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA), kami kerap menerima warga yang datang untuk berkonsultasi tentang berbagai persoalan rumah tangga. Dari sekian banyak kisah yang disampaikan, kami menangkap satu benang merah yang sama: prahara rumah tangga sering kali bukan dipicu oleh persoalan besar, melainkan oleh hal-hal kecil yang diabaikan, terutama minimnya kepekaan dan empati antaranggota keluarga.
Kepekaan dan empati bukanlah sesuatu yang lahir dengan sendirinya. Ia perlu ditanamkan, dipupuk, dan dibiasakan, terutama dalam lingkungan terdekat manusia, yaitu keluarga. Sayangnya, banyak pasangan menganggap sikap peka dan empatik sebagai sesuatu yang sepele, bahkan tidak penting. Padahal, dari situlah keharmonisan rumah tangga bertumbuh atau justru perlahan memudar.
Empati sering disalahpahami hanya sebatas rasa kasihan atau iba. Padahal, empati lebih dalam dari itu. Empati adalah kesadaran sosial—kemampuan untuk merasakan, memahami, dan merespons kondisi orang lain secara tepat. Dalam kehidupan keluarga, empati berarti mampu membaca perubahan suasana hati pasangan, memahami lelahnya tubuh setelah bekerja, atau menangkap diamnya seseorang yang sejatinya sedang membutuhkan perhatian.
Sikap cuek, kurang peduli, dan masa bodoh kerap dianggap wajar. Bahkan, tidak sedikit yang menganggapnya sebagai tanda kedewasaan atau kemandirian. Padahal, dalam konteks rumah tangga, sikap-sikap tersebut justru dapat menjadi bibit renggangnya hubungan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang yang menenangkan, perlahan berubah menjadi ruang sunyi yang dingin secara emosional.
Sering kali, pasangan tidak menuntut hal-hal besar. Bukan hadiah mahal atau pujian berlebihan. Yang dibutuhkan justru hal-hal sederhana: didengar tanpa dihakimi, diperhatikan tanpa diminta, dan ditemani tanpa disuruh. Ketika pasangan terlihat lelah, pertanyaan sederhana seperti, “Apa kamu capek hari ini?” atau tawaran bantuan kecil bisa menjadi penawar yang menenangkan hati. Hal-hal kecil inilah yang justru memperkuat ikatan batin dalam keluarga.
Dalam perspektif nilai-nilai keagamaan, empati merupakan bagian dari akhlak mulia. Rasulullah SAW telah memberi teladan bagaimana beliau bersikap lembut kepada keluarganya, peka terhadap perasaan istri-istri beliau, serta hadir secara utuh—bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Keluarga yang dibangun atas dasar mawaddah wa rahmah meniscayakan empati sebagai fondasi utamanya.
Menumbuhkan empati dalam keluarga juga berarti melatih diri untuk tidak egois. Tidak selalu merasa paling lelah, paling benar, atau paling berat bebannya. Setiap anggota keluarga memiliki cerita, beban, dan perjuangan masing-masing. Ketika empati tumbuh, komunikasi menjadi lebih sehat, konflik lebih mudah diredam, dan rasa saling percaya akan semakin kuat.
Sebaliknya, kurangnya empati dapat menekan jiwa dan perasaan pasangan. Tekanan batin yang berlangsung lama bukan hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Sikap merasa paling pintar, meremehkan perasaan pasangan, atau menutup ruang dialog perlahan akan melukai, meski sering kali tidak disadari.
Kepekaan dan empati memang tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa dibiasakan. Dimulai dari hal-hal kecil: mendengarkan tanpa menyela, tidak meremehkan keluhan, serta hadir ketika pasangan membutuhkan. Dari kebiasaan-kebiasaan sederhana itulah kesadaran sosial dalam keluarga akan tumbuh secara alami.
Keluarga yang hangat bukanlah keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang anggotanya saling peduli. Bukan rumah yang megah, tetapi hati yang lapang. Karena pasangan yang lelah tidak selalu membutuhkan solusi—sering kali, ia hanya ingin ditemani dan dipahami. []
*Penulis adalah Penghulu Ahli Madya dan Kepala KUA Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.