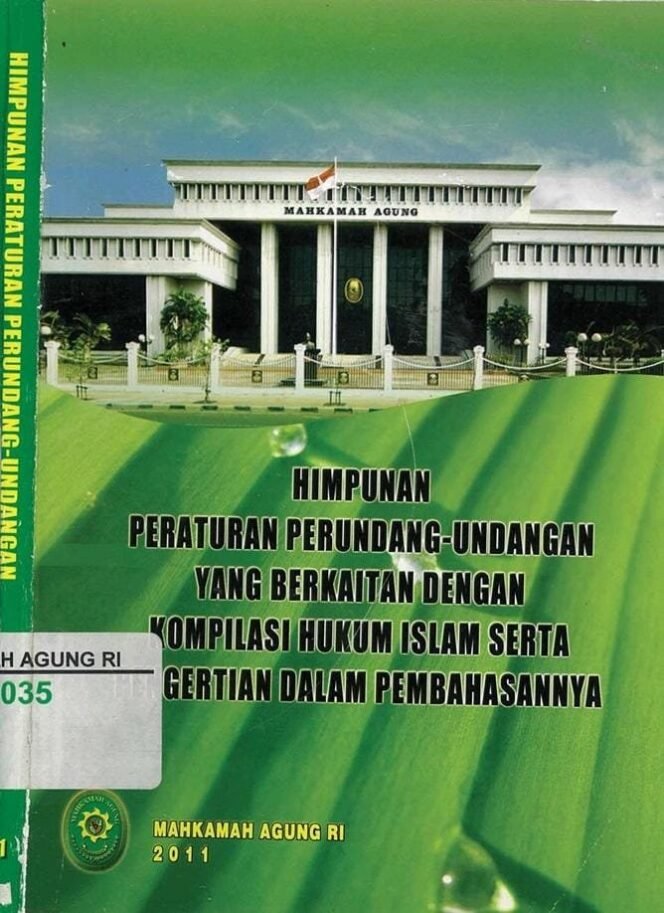Di beberapa tulisan yang lalu, penulis telah menyinggung bahwa mazhab fikih yang diadopsi dalam regulasi Indonesia terkait kawin hamil dan status nasab anak zina adalah Hanafi. Hal ini seiring dengan kecocokan isi regulasi dengan penjelasan dalam beberapa literatur fikih Hanafi, seperti penjelasan Ibn Mazah dalam Al-Muhith al-Burhaniy. Regulasi Indonesia yang dimaksud di sini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Dalam edisi KHI yang penulis dapatkan, yakni yang berjudul Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya terbitan 2011 oleh Perpustakaan dana Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, dijelaskan bahwa landasan (dalam artian sebagai dasar hukum) keberadaan KHI adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
Dalam edisi tersebut dijelaskan bahwa isi dari dua landasan ini intinya bahwa KHI harus dipakai dalam masalah (dalam konteks MA, diksi yang digunakan lebih mengarah kepada sengketa-sengketa) perkawinan, perwakafan, dan kewarisan. Selain itu, KHI juga memiliki kedudukan yang sederajat (kesederajatan) dengan peraturan perundang-undangan perkawinan, perwakafan, dan kewarisan.
Pada ranah implementasi, KHI ini harusnya menjadi pedoman bagi seluruh stake holder dalam bidang perkawinan, perwakafan, dan kewarisan, yang dalam konteks tulisan ini memasukkan penghulu di dalamnya. Penghulu dalam ‘ijtihad’-nya sudah seharusnya merujuk pada KHI selain peraturan perundang-undangan yang berlaku kendatipun ‘bertentangan’ dengan mazhab yang dianut olehnya. Kenyataannya, apa yang tersaji di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Mayoritas fikih yang dianut di Indonesia, tak terkecuali oleh penghulu, adalah mazhab Syafii. Dominasi ini dirasakan secara sadar atau tidak telah memberi pengaruh terhadap setiap kebijakan ‘ijtihad’ yang diambil. Faktor yang mungkin saja menyebabkan hal tersebut terjadi adalah pemahaman yang lebih komprehensif di banding mazhab yang lain.
Dalam masalah kawin hamil dan status nasab anak zina, hasil diskusi, perbincangan, serta wawancara dengan beberapa penghulu yang penulis lakukan mendapati bahwa hanya sedikit saja dari para penghulu yang secara konsisten menerapkan KHI secara utuh. Artinya, lebih banyak penghulu yang melakukan perilaku ‘mendua’, dalam arti, tertib administrasinya mengikuti KHI, tetapi real praktik di lapangannya mengikuti mazhab Syafii yang mereka anut.
Gambarannya seperti ini, KHI mengakui ayah biologis sebagai ayah kandung dari anak yang dilahirkan dalam kawin hamil. Oleh karenanya ada implikasi hubungan nasab di antara keduanya. Karena memiliki hubungan nasab, si ayah biologis memiliki hak perwalian atas si anak. Penghulu seharusnya mengikuti regulasi tersebut dan ‘mengakui’ hubungan nasab keduanya. Kenyataannya, sebagian penghulu justru beralih kepada mazhabnya sendiri (Syafii) sehingga menerapkan kebijakan wali hakim.
Peralihan mazhab penghulu ini merujuk pada pendapat yang dikutip Syekh Zain al-Din al-Malibariy dalam Fath al-Mu‘in dari Al-Mawardiy, diperbolehkan bagi seorang kadi (qadliy) atau penggantinya. Dalam ijtihadnya, kadi boleh beralih kepada pendapat selain imam mujtahid yang diikutinya. Aplikasinya pada masalah ini, penghulu yang mengikuti mazhab Syafii diperbolehkan untuk mengikuti pendapat mazhab Hanafi terkait dengan masalah kawin hamil dan status nasab anak zina yang tengah ia hadapi.
(مهمة) يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا. وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده. وقال الماوردي وغيره: يجوز. (فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 248)
Karena dianggap tidak konsisten terhadap regulasi yang ada (KHI), perilaku ‘mendua’ penghulu ini kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Karena penghulu sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi ‘tidak mengakui’ regulasi yang ditetapkan oleh Negara. Sementara dalam rujukan yang lain juga ditemukan penjelasan,
حكم الحاكم يرفع الخلاف
“Hukum (yang dipilih oleh) hakim menghilangkan perbedaan pendapat (mazhab).”
Artinya ketika Negara (al-hakim) telah menetapkan satu mazhab tertentu maka segala perbedaan pendapat yang ada menjadi gugur.
Penulis sendiri sering kali mempertanyakan perilaku ‘mendua’ ini. Jika ada mazhab yang telah mengakui hubungan nasab anak zina pada kawin hamil, mengapa harus ‘repot’ beralih ke mazhab sendiri yang ‘bertentangan’? Malah jangan-jangan, dengan mengikuti mazhab sendiri yang menafikan hubungan nasab dan beralih ke wali hakim justru menjadikan nikahnya tidak sah, karena dengan adanya kawin hamil wali nasabnya menjadi diakui? Wallahu a‘lam bi al-shawab. []