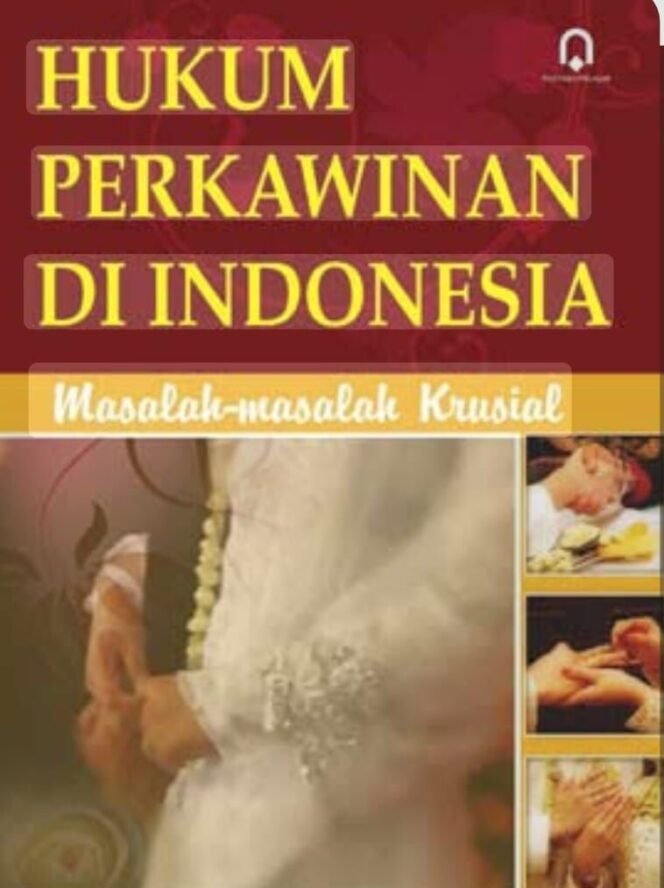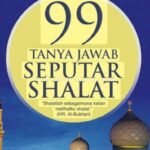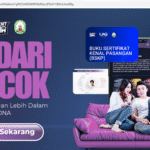Hukum Perkawinan di Indonesia (I)
Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.
Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkan baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah.1
Keinginan masyarakat akan undang-undang perkawinan (UUP) dilatarbelakangi berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan atau hubungan antara suami dan isteri. Hal ini tercermin dalam tuntutan organisasi-organisasi, terutama organisasi wanita hingga sampai pembicaraannya di Volksraad (Dewan Rakyat). Persoalan-persoalan perkawinan ini pulalah yang membuat kaum wanita Indonesia mengadakan kongres pada tahun 1928 membahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam, yakni perkawinan kanak- kanak, kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain.2 Selain faktor yang terebut di atas, yang memicu masyarakat akan kehadiran UUP adalah hukum perkawinan yang diatur di dalam fiqh
dirasakan oleh sebagian orang sudah kehilangan kemaslahatannya atau manfaatnya. Jadi, sebagian umat Islam Indonesia menuntut pemerintah supaya diujudkan suatu peraturan yang dapat melindungi hak-hak wanita dan anak-anak mereka.3
Setelah Indonesia merdeka pemerintah berupaya untuk mewujudkan peraturan perkawinan tersebut, hal ini telah dimulai sejak tahun 1950, di mana pemerintah RI berhasil mengeluarkan Surat Keputusan, yakni Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.4
Beberapa tahun kemudian, setelah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan baru, panitia tersebut dapat menyelesaikan sebuah RUU tentang Perkawinan untuk umat Islam. Tapi RUU yang pernah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh pemerintah pada tahun 1958 tidak sempat menjadi undang-undang karena DPR pada waktu itu menjadi beku setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.5
Setelah itu, antara tahun 1960 dan 1963, tercatat tiga kali pertemuan yang antara lain membicarakan masalah hukum perkawinan dan perundang-undangannya, yaitu:
- Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga yang diadakan oleh Departemen Sosial pada tahun 1960.
- Konperensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Agama pada tahun
- Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) pada tahun 1963.6 3 Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Kesejarahan dan Metodologis, (Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 45.
4 Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan … hlm. 9.
5 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, … hlm. 1.
6 Ibid., hlm. 1-2.
Dalam tahun 1966 Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapannya Nomor XXVII/MPRS/1966 menyatakan dalam Pasal I ayat 3 bahwa perlu segera diadakan undang-undang tentang perkawinan.7
Pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah RUU kepada DPRGR:
- RUU tentang Pernikahan umat
- RUU tetang Ketentuan Pokok
Kedua RUU yang dibicarakan oleh DPRGR dalam tahun 1968 itu tidak mendapat persetujuan DPRGR, maka tidak menjadi undang- undang. Karena itu oleh pemerintah kedua RUU itu ditarik kembali.8 Sampai berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden RI yang disebut masa Orde Lama, UUP yang sangat didambakan oleh
umat Islam Indonesia ternyata belum juga terujud.
Setelah Orde Lama, muncul Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Di masa Orde Baru ini, kelompok agama semakin terpuruk dan posisi mereka sebagai underdog dipentas politik nasional semakin nyata. Sekularisme menjadi politik rezim Orde Baru, sehingga bermunculan kebijakan sosial politik yang secara sistimatis bertujuan menyingkirkan kelompok agama dari pentas politik nasional.9 Menurut Liddle sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Sirozi, bahwa rezim Orde Baru menerapkan “special policies” atau kebijakan khusus terhadap tokoh-tokoh agama yang kritis. Aktivitas politik kelompok ini terus dikontrol, hak-hak politik mereka dikurangi dan munculnya kelompok-kelompok tandingan conperative rezim dengan Orde Baru.10
Sekalipun rezim Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto memerjinalkan dan hampir tidak memperhatikan ajaran hukum
7 Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia … hlm. 45-46.
8 Ibid., hlm. 46.
9 Muhammad Sirozi, Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi, (Yogyakarta: AK Group, 2004), hlm. 24.
10 Ibid.
Islam, syariat Islam hanya diamalkan oleh masing-masing individu yang beragama Islam, namun tuntutan umat Islam terhadap UUP tetap berjalan. Terutama tuntutan tersebut datang dari golongan wanita, seperti Ikatan Sarjana Wanita (ISWI) dalam simposiumnya pada tanggal 29 Januari 1972. Demikian pula Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972 mendesak kepada pemerintah supaya mengajukan kembali kedua RUU tentang Perkawinan yang pernah tidak disetujui DPRGR yang lalu kepada DPR hasil Pemilihan Umum 1971.11
Setelah bekerja keras pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU tentang Perkawinan yang baru, dan pada tahun 1973, tepatnya tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru itu kepada DPR.12
RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah Orde Baru ke DPR, oleh Hefner dan Santoso, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Sirozi disebut “anti Islamic”, yaitu RUU tentang Perkawinan yang sangat membatasi kewenangan Pengadilan Agama. Namun akhirnya RUU tersebut dirubah atas tekanan tokoh-tokoh agama.13 Menurut K. Wantjik Saleh, ketika RUU tersebut disampaikan oleh pemerintah, telah timbul kehebohan karena beberapa pasal dari RUU tersebut terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan asas-asas ajaran dan hukum Islam tentang perkawinan. Tapi, syukur alhamdulillah berkat kebijaksanaan pemerintah dan DPR serta dukungan masyarakat, pasal-pasal yang tidak dikehendaki oleh umat Islam tersebut dapat disingkirkan, sehingga menjelmalah menjadi undang-undang yang sekarang ini.14
Setelah melalui proses yang cukup lama, supaya undang-undang tersebut dapat diterima semua pihak, akhirnya pada tahun 1974,11 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, … hlm. 2.
12 Ibid.
13 Muhammad Sirozi, Catatan Kritis … hlm. 25-26.
14 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, … hlm. 2-3.
tepatnya tanggal 2 Januari 1974 disahkan oleh Presiden RI dan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974).
Prof. Dr. Hazairin dalam bukunya “Tinjauan Mengenai Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”, menamakan undang-undang ini, sebagai suatu “unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.15
UU No. 1/1974 Pasal 67 menentukan:
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan
- Hal-hal dalam undang-undang ini memerlukan mengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa UU No. 1/1974 sebenarnya sudah berlaku sejak pengundangannya pada tanggal 2 Januari 1974, hanya saja untuk pelaksanaannya secara efektif diatur oleh suatu Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat disadari karena UU No. 1/1974 ini, disamping mengatur ketentuan-ketentuan yang pokok tentang perkawinan juga banyak memuat ketentuan-ketentuan yang menghendaki pelaksanaannya.
Syukurlah, setelah UU No. 1/1974 ini berlaku satu tahun lebih, tepatnya pada tanggal 1 April 1975 diundangkanlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9/1975) guna untuk memenuhi janji Pasal 67 UU No. 1/1974.
Pasal 49 PP No. 9/1975 menyatakan: 15 Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1-1974, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1986), hlm. 1.
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Diciptakannya PP No. 9 /1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 ialah untuk melancarkan pelaksanaan saat mulai pelaksanaan UU No. 1/1974 secara efektif.
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Istilah “kompilasi” diambil dari perkataan “compilare” dalam bahasa Latin yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “compilation” dalam bahasa Inggris atau “compilatie” dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir.16
Ditinjau dari segi bahasa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.17 Sedangkan kompilasi dalam pengertian hukum adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan- bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.18
Akan tetapi, dilihat dari kegiatan penyusunan kompilasi hukum Islam, yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber 16 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10.
17 Ibid., hlm. 11.
18 Ibid., hlm. 12.
pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.19
Ide untuk melahirkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) ini timbul setelah Mahkamah Agung (MA) membina bidang justisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pegadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh MA, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.20
Pada tahun 1989 lahir Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama,21 undang ini juga mengatur tentang hukum formil,19 Ibid., hlm. 14.
20 Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 21.
21 Dengan lahirnya UU. No. 7/1989 ini menjadikan status PA sejajar dengan peradilan- peradilan lainnya. Tokoh-tokoh agama yang kritis menilai undang-undang ini sebagai refleksi syariah.
DASAR-DASAR HUKUM PERKAWINAN
Pengertian Perkawinan.
Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana ditemui dalam beberapa kamus, di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan 1. Perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri; nikah, 2. (sudah) beristeri atau berbini, 3. Dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.39 Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau isteri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh”.40
Dalam buku fiqh ditemui dua kata untuk perkawinan atau pernikahan, yakni al-nikah/النـكاح dan al-ziwaj/الزواج. Secara harfiah, al-nikah berarti al-wath’u/الوطأ, al-dhdammu/الضـم dan al-jam’u/الجـمع.41 Kata al-wath’u berasal dari kata wath’a – yath’u – wath’an (– يـطأ – وطأ وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, 39 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 453.
40 Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Cita Media Pres, tt), hlm. 344.
41 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.19
menaiki, menggauli dan bersetubuh, atau bersenggama.42 Sedangkan Amir Syarifuddin mengartikan kata nikah adalah “bergabung” (ضـم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عـقـد).43
Kata al-dhammu, yang terambil dari akar kata dhamma – yadhammu – dhamman (ضـمـا – يـضـم – ضـم), secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.44 Sedangkan kata al-jam’u yang berasal dari akar kata jama’a – yajma’u – jam’an (جـمـعـا – يـجـمـع – جـمـع) berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabung, menjumlahkan dan menyusun.45 Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau senggama dalam istilah fiqh disebut dengan al-jima’ mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam’u.46
Selain kata al-nikah dipergunakan juga kata al-zawaj/al-ziwaj. Terambil dari akar kata zaja – yazaju – zaujan (زوجا – يـزاج – زاج) yang secara harfiah berarti menghasut, menabur benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan al–zawaj/al-ziwaj di sini ialah al-tazwij yang terambil dari kata zawwaja – yuzawwiju – tazwijan (تـزويـجـا – يـزّوج – زّوج) dalam bentuk timbangan “fa’ala – yufa’ilu – taf ’ilan (تـفـعـيـلا – يـفـّعـل – فـّعـل) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.47 Selain itu arti dari kata nikah sering pula dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk akad nikah,48
Pengertian nikah yang terakhir ini sering juga digunakan kata kawin atau nikah. Kata kawin, boleh jadi maksudnya adalah
42 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Qamus Arab – Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1671-1672.
43 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam … hlm. 36.
44 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Qamus … hlm. 887.
45 Ibid., hlm. 225
46 Summa, Hukum Keluarga Islam … hlm. 43.
47 Ibid.
48 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cet. ke III, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.
20 HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
hubungan seksual atau coitus, sedangkan nikah mengandung arti akad perkawinan yang berdasarkan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Seperti ucapan “kawin sih sudah, tetapi nikah belum”. Kata nikah dimaksudkan pula perkawinan manusia, sedangkan kawin untuk binatang.
Pemakaian yang masyhur untuk kata “nikah” adalah tertuju pada “akad”. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syari’at. Di dalam al-Quran pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.49
Sedangkan arti perkataan “nikah” dari segi terminologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama fiqh di dalam buku- buku fiqhnya, ditemukan beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan rumusan tersebut disebabkan perbedaan pandangan para ulama di dalam memahami perkataan nikah tersebut, antara lain:
عـقـد يـتـضـمـن ابـاحـة الـوطء بـلـفـظ الانـكاح او
تـزويـج5
Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa- ja.
Definisi nikah di atas, dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah. Para ulama di kalangan Syafi’iyah ini melihat kepada hakikat dari akad nikah itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul. Sedangkan sebelum akad nikah tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.51 Selanjutnya, Amir Syarifuddin menjelaskan, bahwa difinisi
tersebut mengandung maksud sebagai berikut: 49 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Cet. ke I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.
50 Ibnu Hazmin, al- Mahaaly, Jilid III, (Mesir: Mathba’ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970), hlm. 206.
51 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam…, hal.37.
Dr. Yuliatin, S.Ag, M.H.I. – Drs. Baharuddin Ahmad M.H.I. 21
- Pertama: penggunaan lafaz akad (عــقـــد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- Kedua: penggunaan ungkapan; الوطء ابـاحــة يـتـضـمـن Artinya: yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara’. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.
- Ketiga: menggunakan kata تـزويـــج او انـــكاح بـلـفـــظ Artinya: menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja, mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki- laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena awal Islam di samping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “tassari”.52
Menurut hemat penulis, definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sebagaimana definisi yang dikemukakan di atas sangat kaku dan sempit, sebab nikah didefinisikan hanya sebagai perjanjian legalisasi hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda yang pada asalnya terlarang. Seolah-olah hakikat perkawinan itu hanya melampias nafsu syahwat saja, upaya penghindaran diri dari dosa akibat perzinaan, atau pelegalisasian hubungan antara pria dan 52 Ibid., hal. 38.
wanita saja. Sedikit pun tidak tersirat dalam definisi tersebut suatu yang karenanya membuat arti perkawinan lebih mulya dibandingkan sebagai pelempiasan kebutuhan biologis semata.
Dalam kaitan untuk menghilangkan image masyarakat tentang arti nikah, sekaligus menempatkan perkawinan sebagai suatu yang mempunyai kedudukan yang mulia, maka ulama kontemporer berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, memberikan gambaran yang komprehensif bila dibandingkan dengan definisi nikah yang sebelumnya.
Di antaranya dikemukakan oleh Muhammad Abu Ishrah, sebagaimana yang dikutip oleh Tim Penulis Buku Ilmu Fiqh II Departemen Agama RI sebagai berikut:
عـقـد يـفـيـد حـلّ الـعـشـرة بـيـن الـرجـل والـمـرأة وتـعـاونـهـمـا ويـحـد مـالـكـلـيـهـمـا من حـقـوق ومـاعـليـه من واجـبـات.
Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.53
Kalau diperhatikan rumusan definisi tersebut juga mengandung definisi yang pertama, yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menisyaratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, aspek ta’awun (tolong menolong). Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya. Dari definisi terakhir itu, tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang
diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.53 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), II : 37.
Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (mitsaqan galidzan), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.
Dari uraian tentang pengertian perkawinan di atas, dapat ditegaskan sebagai berikut: Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi tugasnya, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah SWT.
Pengertian perkawinan yang dikemukakan ulama mutaakhirin di atas, selaras dengan pengertian yang dikemukakan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP), yang berbunyi sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ada beberapa hal dari rumusan Pasal 1 UUP di atas yang patut untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:
- Pertama: digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh sebagian Negara Barat, termasuk Perancis juga sudah mengesahkan perkawinan
- Dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang Perkawinan yang
dilakukan oleh seorang pria dengan sesama pria (gay) atau antara seorang perempuan dengan seorang perempuan (lesbian) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui di Indonesia. Anak kalimat “antara seorang pria dengan seorang wanita” dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, atau “’aqdun bayn al-rajul wa al-mar’ah” dalam undang-undang perkawinan lainnya, secara eksplisit menegaskan penafian kemungkinan ada perkawinan antara dua orang yang sama jenis.54 Begitu pentingnya perihal keharusan berbeda jenis kelamin dalam suatu perkawinan itu, sampai-sampai mendiang Paus Yohanes Paulus II (1920-2005), yang bernama asli Kartol Wojtila itu pada tahun 2004 sebelum kematiannya kembali mengutuk perkawinan sesama jenis.55
- Kedua: digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- Ketiga: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu “membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal”, maksudnya menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah atau perkawinan kontrak dan perkawinan tahlil.
- Keempat: disebutkannya “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah
Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari petunjuk atau panduan hukum Islam. Pencantuman kata-kata: “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah sebagai bukti, bahwa hukum Islam menjadi pedoman di dalam 54 Summa, Hukum Keluarga Muslim … hlm. 52
55 Ibid.
pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Untuk itu, kata Summa, kita bangsa Indonesia sudah pada tempatnya berterima kasih kepada para penyusun Undang-Undang Perkawinan.56
Di samping definisi yang dikemukakan oleh UUP, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dari pada definisi yang dikemukakan di dalam UUP tersebut, namun sifatnya menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2 KHI).
Ungkapan: “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan UUP yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UUP. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama atau sakral dan oleh karena itu orang
yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.
Hukum Perkawinan.
Hukum asal pernikahan, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan penafsiran terhadap ayat tentang nikah. Di antara mereka, seperti Imam Abu Daud Adz-Dzahiri berpendapat bahwa, nikah itu asal hukumnya wajib. Adapun Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa nikah itu hukumnya mubah.57
Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan, sebagaimana yang dikutip oleh Ghazali:
Segolongan fuqaha, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. 56 Ibid.. hlm. 53.
57 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan … hlm. 14.
Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian orang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.58
Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah? Ayat tersebut di antaranya adalah:
فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَْٰن وَثَُٰلثَ وَرَُٰبعَ……
…Maka kawininlah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat …
Di antara hadits yang berkenaan dengan nikah ini adalah:
تَـنَـاكَـحُـوا فَـإِنِّ مُـكَاثِـرٌبِكُـمُ الَمَـمُ …
Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lalu. …
Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.
Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara’ yang lima, adakalanya haram, makruh, sunnat (mandub) atau adakalanya mubah.5958 Ghazali, Fiqh Munakahat, … hlm. 16.
59 Abdul Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arbaah, (Mesir: Dar al- Irsyad, tt.), Jilid ke 7, hlm. 4.
Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia lebih dekat dan lebih banyak mengamalkan pandangan ulama Syafi’iyah.
Terlepas dari pendapat Imam Mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Quran maupun al-sunnah, Islam sangat menganjurkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.60
- Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum malakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan itupun wajib, sesuai dengan qaedah:
مَـالَا يَـتِمُّ الـوَاجِـبَ إِلَّا بِـهِ فَـهُـوَ وَاجِـبٌ
“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya wajib”.
Qaedah lain menyebutkan:
لِلْـوَسَـائِـلَ حُـكْـمُ الـمَـقَـاصِد.
“Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju”.
Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan ma’siyat.60 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, …, hlm. 59-62.
- Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunah
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melansungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran al-Quran seperti tersebut dalam surat al-Nur ayat 32 dan hadits Nabi SAW. Baik al-Quran maupun hadits Nabi SAW tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qarinah-qarinah yang ada,
- Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram
Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَ ٱلَّتهْلُكَةِ……
… dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, …
Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menterlantarkan orang lain, masalahnya wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.
- Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin.