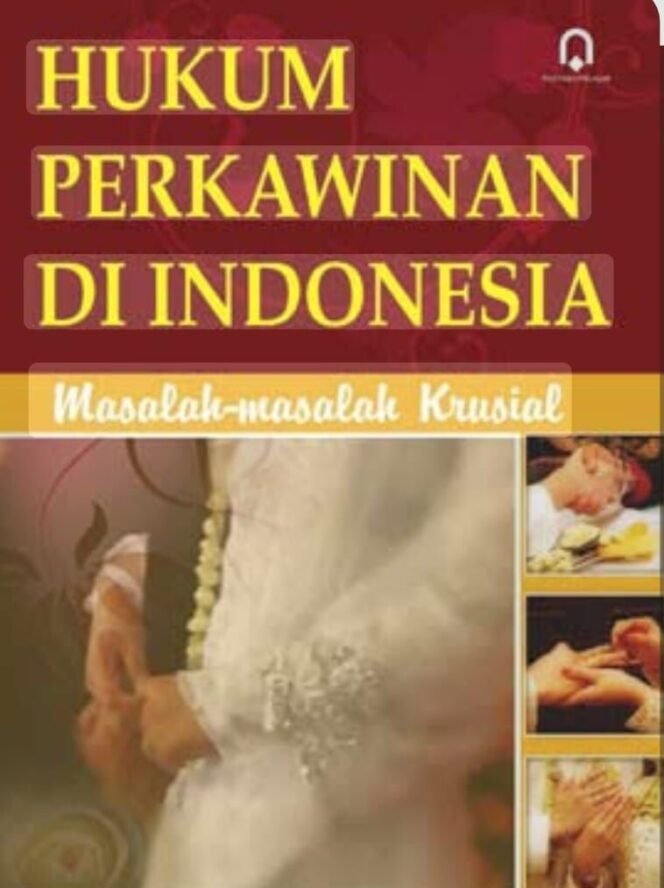Hukum Perkawinan di Indonesia (III)
Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat.
Perkawinan merupakan hubungan hukum yang sangat istimewa, karena ia dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki- laki dengan seorang wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman, serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah SWT. Di samping itu, perkawinan mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis dan afeksional. Aspek biologis adalah kebutuhan manusia untuk mendapat keturunan, sedangkan aspek afeksional adalah kebutuhan manusia pada ketenangan dan ketenteraman berdasarkan kasih sayang.115 Menurut istilah Shahrur perkawinan itu terdapat dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (mihwar al-‘alaqah al-jinsiyyah). Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (mihwar al-‘alaqah al-insaniyyah al-ijtima’iyyah).116
115 Saifullah, Perkawinan Antar Agama: Tinjauan Hukum dan Psikologi, dalam Mimbar Hukum No. 32 Tahun VIII, (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA, 1997), hlm. 50.
116 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, alih bahasa Sahiron
Para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat menetapkan adanya rukun dalam perkawinan. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan salah satu rukun dari perkawinan tersebut. Ulama Malikiyah umpamanya, mereka menetapkan rukun perkawinan itu ada lima, yakni wali, mahar, calon suami, calon isteri dan shigat.117 Ulama Syafiyyah menetapkan rukun perkawinan juga lima, tapi tidak termasuk mahar, yang menjadi rukun perkawinan menurut mereka adalah: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan shigat.118 Sedangkan Abdurrahman al- Jaziry di dalam bukunya meyimpulkan, bahwa yang termasuk rukun perkawinan adalah al-ijab dan al-qabul, di mana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.119 Sayyid Sabiq juga menyimpulkan, bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari al-ijab dan al-qabul.120 Sedangkan yang lainnya termasuk ke dalam syarat perkawinan. Jelaslah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang rukun perkawinan. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan rukun perkawinan, maka KHI mengatur rukun perkawinan dalam Pasal 14 berbunyi sebagai berikut,121 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
- Calon suami
- Calon isteri
- Wali nikah
- Dua orang saksi, dan
- Ijab dan qabul.
Sedangkan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun perkawinan. Jadi masing-masing rukun memiliki syarat-syarat Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yokyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 434-435
117 Abdurahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh … hlm. 12.
118 Ibid.
119 Ibid.
120 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, … hlm. 29.
121 UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 tidak mengatur tentang rukun perkawinan, hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan saja. Pada hal rukun perkawinan sangat penting sekali, karena tanpa rukun perkawinan, tentu saja perkawinan tersebut tidak akan dapat dilangsungkan.
Kelima rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh di dalam buku-buku fiqh, adalah sebagai berikut:
- Calon suami, syarat-syaratnya:
- Beragama Islam;
- Laki-laki;
- Jelas orangnya;
- Dapat memberikan persetujuan, dan
- Tidak terdapat halangan
- Calon isteri, syarat-syaratnya:
- Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
- Perempuan;
- Jelas orangnya;
- Dapat dimintai persetujuan, dan
- Tidak terdapat halangan
- Wali nikah, syarat-syaratnya:
- Laki-laki;
- Dewasa;
- Mempunyai hak perwalian, dan
- Tidak terdapat halangan
- Dua orang saksi, syarat-syaratnya:
- Minimal dua orang laki-laki;
- Hadir dalam ijab dan qabul;
- Dapat mengerti maksud aqad;
- Islam, dan
- Ijab dab qabul, syarat-syaratnya:
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami;
- Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- Antara ijab dan qabul bersambungan;
- Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, dan
- Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang 122
Syarat-syarat Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan.
Syarat-syarat perkawinan menurut ulama fiqh tersebut di atas, dilengkapi pula dengan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia. Di antara syarat- syarat yang diatur dalam fiqh, berdasarkan analisis perundang- undangan ternyata bertentangan dengan syarat-syarat yang diatur dalam UUP, dengan demikian, karena mengingat maslahahnya, maka syarat tersebut tidak berlaku lagi sebagai syarat perkawinan.
Menurut ketentuan undang-undang, bahwa syarat-syarat perkawinan itu terdiri dari syarat materiil dan syarat administratif atau disebut juga dengan syarat formiil.123 Masing-masing rukun perkawinan dilengkapi pula dengan beberapa syarat materiil sebagai berikut:
Calon Suami dan Isteri
Menurut hemat penulis, berdasarkan ketentuan UUP, baik menurut
- No. 1/1974, PP. No. 9/1975 dan KHI, maka yang menjadi syarat bagi calon suami dan isteri adalah sebagai berikut: 122 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam… hlm. 62. Lihat Muhammad Baqir al-Habsyi, Fiqih Praktis, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 71. Lihat Baharuddin Ahmad dan Fauzi Muhammad, Nikah Beda Agama Analisis Perundang- Undangan dan Fatwa MUI, Cet. ke I, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 33-34.
123 Menurut Asmin, syarat-syarat perkawinan itu dibagi dua, yakni: Syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat formiil menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Lihat Asmin, Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau dari UUP No. 1/1974, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hlm 22.
- Beragama Islam
Syarat tersebut dapat dipahami dari Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1/1974, pasal tersebut berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
Dalam penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ini dan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan ajaran Islam, seperti “Perkawinan didasarkan (pada) Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1), Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar agama” (Pasal 29), dan sebagainya menunjukkan bahwa agama diberi peranan yang besar dalam mengatur hidup dan kehidupan keluarga.124
Demikian pula halnya dengan perkawinan yang berlaku di Indonesia, tetap mengacu kepada agama yang dianut oleh warga Indonesia. Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing penganutnya.
Ahmad Sukarja dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa UUP yang dibentuk atas dasar UUD 1945 itumenempatkan agama sebagai penentu sahnya suatu perkawinan. Berdasarkan ketentuan sahnya perkawinan atas dasar agama, perkawinan yang dianut di Indonesia adalah religious marriage yaitu perkawinan berdasarkan agama. Ketentuan ini mengakhiri berlakunya civil 124 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 24.
marriage (perkawinan perdata), suatu perkawinan yang sekuler yang dirumuskan dalam Pasal 26 KUHP (BW) yang menyatakan “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”.125
Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/ Katolik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.126
Hazairin di dalam bukunya berkesimpulan, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.127
Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UUP ini, peranan agama sangat menentukan untuk keabsahan suatu perkawinan. Malah menurut Amir Syarifuddin, Guru Besar Hukum Islam dari IAIN Imam Bonjol Padang, mengatakan “telah memenuhi ketentuan umum dengan tidak bertentangan hukum nasional dengan hukum agama”.128 Ideal atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada standard yang digunakan masyarakat. Secara garis besar, pada waktu ini ada dua standard besar yang digunakan oleh masyarakat dalam menata hidup mereka. Pertama adalah humanisme dan kedua adalah agama.129 Pada yang pertama, segala nilai dikembalikan kepada manusia yang berdaulat penuh atas dirinya, dan pada yang kedua, dikembalikan kepada Allah sebagai Pencipta manusia yang mengatur tentang tata kehidupan manusia.130
Menurut Rifyal Ka’bah salah seorang Hakim Agung RI, perkawinan yang ideal bagi masyarakat Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Inilah standard yang dipilih oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.131
Berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas serta tanggapan dari para pakarnya, maka menurut hemat penulis, calon suami dan isteri disyaratkan beragama Islam, sekalipun ketentuan ini tidak ditemukan pada bab yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan.
Bila diperhatikan ketentuan dalam KHI, maka KHI lebih tegas lagi menentukan, bahwa bagi umat Islam perkawinan yang sah itu adalah bila dilakukan secara hukum Islam. Pasal 4 KHI menegaskan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
Anjuran Rasulullah SAW. supaya memilih yang beragama (Islam), seharusnya menjadi prioritas pilihan utama dari yang lainnya, hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:
عـن ابى هـريـرة رضـى الـله عـنه عـن الـنبي صـلـعـم قـال تـنكـح الـمـرأة لاربع لـمـالـها ولـنــسـابـها ولـجـمـالـها ولـديـنـهـافـاظـفـربـذاتالديـنتـربتيـداك)مـتفقعـلـيه(
129 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 51.
130 Ibid.
131 Ibid., hlm. 52.
Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu”. (Muttafaq ‘Alaih).
Selain Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1/1974, KHI juga mengatur larangan kawin dengan non Islam, hal ini diatur dalam Pasal 40 dan 44. Pasal 40 KHI berbunyi:
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
- karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria
- seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria
- seorang wanita yang tidak beragama
Sedangkan Pasal 44 menyatakan: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
Jadi KHI melalui Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 menentukan bahwa seorang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun wanitanya dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang bukan beragama Islam.
Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 telah menfatwakan, bahwa haram hukumnya nikah dengan yang bukan beragama Islam. Fatwa keharaman kawin dengan non-Islam ini kembali ditetapkan pada tahun 2005. Pertimbangan kedua fatwa ini adalah memperhatikan perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan keresahan dan membingungkan masyarakat serta membawa mafsadah bagi Islam itu sendiri. Berdasarkan suatu qaedah, maka mencegah umat Islam nikah dengan non-Islam itu lebih baik dan lebih utama dilakukan. Bunyi qaedah tersebut adalah:
دَرْءُ المَـفَاسِـدِ مُـقَـدَّمٌ عَـلَ جَـلْبِ الـمَـصَـالِـحِ
Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1/1974, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI dan fatwa MUI tahun 1980 dan 2005, maka penulis berkesimpulan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah calon suami dan isteri disyaratkan beragama Islam.
- Persetujuan kedua calon mempelai
Persetujuan kedua calon mempelai merupakan salah satu syarat untuk melangsung perkawinan, hal ini ditentukan di dalam Pasal 6 ayat (1) UUP jo Pasal 16 ayat (1) KHI, yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini sangat penting artinya bagi suami dan isteri. Karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan isteri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya, bahwa syarat penting untuk melangsungkan perkawinan adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak,132 tanpa ada paksaan dari pihak manapun.133
Pasal 6 ayat (1) UU. No. 1/1974 mengandung prinsip kebebasan kemauan yang sangat baik. Buat umat Islam ketentuan tersebut sekali-kali tidak bertentangan dengan al- Quran, sesungguhnya mungkin bertentangan dengan hukum fiqh mazhab Syafi’i yang dianut.134
Menurut Ahmad Rafiq, persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah). Karena persetujuan tidak mungkin – atau setidak-tidaknya – sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak mengenal atau mengetahuinya. Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau Pegawai Pencatat, sebelum akad nikah dilangsungkan.135
Di kalangan ulama fiqh berbeda pendapat tentang persetujuan wanita yang akan dinikahkan. Imam Malik, Syafi’i dan Ibnu Abi Laila, berpendapat bahwa gadis dewasa harus diminta persetujuannya. Demikian pula wanita-wanita janda yang sudah dewasa harus diminta persetujuannya.136
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa terhadap anak wanita yang belum dewasa dapat dinikahkan secara paksa oleh walinya tanpa izin dari anak wanita tersebut. Imam Syafi’i berpendapat bahwa anak gadis yang belum dewasa hanya boleh dikawinkan oleh kakek atau ayahnya saja.137
Menurut sebagian pakar hukum di Indonesia tentang Pasal 6 ayat (1) UU. No. 1/1974 jo Pasal 16 ayat (1) KHI, di mana orang tua/wali tidak boleh memaksa anak untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya, atau belum bersedia untuk kawin.138 Apalagi untuk masyarakat yang sudah maju tidak pantas lagi kawin dipaksa, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.139 Dengan adanya ketentuan tersebut, kiranya dapat dihindari praktek “kawin paksa” yang dahulu banyak terjadi.140
Syarat perkawinan yang diatur dalam UUP dan KHI ini selaras dengan bunyi hadits Rasulullah SAW berikut: 135 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, … hlm. 74.
136 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, alih bahasa Imam Ghazali Said dan A. Zaitun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Jilid III, hlm. 9.
137 Ibid., hlm. 13.
138 Hilman Hadikusomo, Hukum Perkawinan Indonesia … hlm. 45.
139 Ibid.
140 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, … hlm. 25.
الـثـيـب احـق بـنـفـســهـا مـن ولـيـهـا والبـكـر تـسـتأذن واذنـها سـكـوتـهـا. رواه مـسـلم
Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada gadis (perawan) diminta persetujuannya, jika diminta (gadis itu) diam. H. R. Muslim.
Hadits lain diriwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:
لا تـنـكـح الايـم حـت تـسـتـأمـر ولا تـنـكـح البـكـر حـت تـسـتـأذن قـالـوا يـارسـول الـلــه وكـيـف اذنــهـا قـال ان تـسـكـت. مـتـفـق عــلـيــه
Tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga diminta persetujuannya, demikian juga tidak dapat dinikahkan gadis, sebelum dimintai izin. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah SAW, bagaimana izinnya? Beliau menjawab: “Apabila ia diam”. (Muttafaq ‘Alaih).
Secara rinci bentuk persetujuan dari wanita yang dimintai persetujuannya, dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) KHI: “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”. Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) menanyakan kepada
mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KHI:
- Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi
- Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat
- Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
Menurut Yahya Harahap, ketentuan Pasal 16 dan 17 KHI merupakan penekanan terutama diberikan kepada calon mempelai wanita untuk melakukan penolakan. Dengan demikian “birrul walidain” tidak boleh dipakai sebagai dasar bagi orang tua untuk melaksanakan perkawinan putrinya. Dengan kata lain bahwa kedua pasal ini tidak diperbolehkan “kawin paksa”.141
Ketentuan di atas dapat juga dipahami sebagai antithesis terhadap sementara anggapan masyarakat bahwa kawin paksa – wali memaksa anak perempuannya dikawinkan dengan laki- laki – masih dibenarkan. Padahal sebenarnya jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memberi petunjuk dalam masalah ini. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:
إن جـاريـة بـكـر اتـت الـنـبي صـلعـم فـذكـرت ان ابــاهـا زوجـهــا وهـى كـارهـة فـخـيـرهــا رسـول الـلـه صـلعـم. رواه احـمـد وابـو داود وابن مـاجـه.
Seorang gadis datang kepada Nabi SAW dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan laki-laki), sementara ia sendiri tidak suka (karahah). Maka Rasulullah SAW mengnjurkannya untuk memilih. (H. R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).
Mengomentari hadits tersebut, Muhammad ibn Ismail al-Shan’any menyimpulkan bahwa hadits tersebut menunjuk haramnya pemaksaan ayah terhadap anaknya yang masih gadis (perawan) untuk kawin. Tetapi al-Baihaqy mendukung pendapat al-Syafi’i yang menilai bahwa hadits Ibn Abbas di atas, laki- laki yang dijodohkannya tidak sesuai (kufu). Dengan kata lain, al-Syafi’i membolehkan seorang ayah memaksa kawin anak gadisnya apabila laki-laki calon suaminya sesuai (kufu).142
Setelah dikemukakan di atas, di mana persetujuan dari calon suami dan calon isteri mutlak diminta persetujuan dan seandainya ada penolakan dari salah satu calon, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Oleh karena itu, pendapat al-Syafi’i di atas telah kehilangan relevansinya. Maksudnya tidak tempatnya lagi nikah paksa di Indonesia, antara calon suami dengan isteri harus sama-sama setuju untuk melangsungkan perkawinannya.
- Umur calon mempelai
Baik UU. No. 1/1974 maupun KHI telah menetapkan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni calon mempelai pria berumur 19 tahun dan calon mempelai perempuan berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) KHI).
Ketentuan batas umur ini, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UUP, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.143 Di samping itu dimaksudkan untuk menghindari adanya perkawinan di bawah umur yang masih sering terjadi di Indonesia.144 Dengan adanya pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan ini, ada kesan bahwa UUP bermaksud untuk merekayasa (untuk tidak mengatakan sebaliknya sah akad yang dilakukan dalam majlis di atas kapal yang sedang berlayar sekalipun. (2). Harus tawafuq artinya ada persesuian isi mengenai maksud ijab dengan maksud qabulnya. (3). Tidak disela- selai oleh ungkapan lain, dan (4). Muwalah artinya berlanjut seketika.173
Perkawinan tidak diatur secara kongret di dalam al-Quran maupun dalam hadits Rasulullah SAW. Sekalipun pencatatan akad nikah itu dipandang sangat penting, namun tidak ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada isyarat bahwa akad nikah itu harus ditulis atau diaktekan. Atas dasar inilah fiqh Islam tidak mengenal adanya
pencatatan perkawinan.174
Menurut Amiur Nuruddin, ada beberapa alasan yang menyebabkan fiqh Islam tidak menjadi perhatian terhadap pencatatan perkawinan, sementara transaksi muamalah sangat dianjurkan oleh al-Quran supaya ada catatan yang jelas. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Quran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimat ul-‘urusy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.175
Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan pada masa awal Islam.
Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta,176 salah satu hasil dari proses pencatatan perkawinan.
Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh ataupun fatwa-fatwa ulama.
Dasar hukum pencatatan perkawinan adalah Pasal 2 ayat (2)
- No. 1/1974, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara KHI mengaturnya di dalam Pasal 5 dan 6.
Pasal 5 menegaskan:
- Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam seti- ap perkawinan harus dicatat. 175 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taregan, Hukum Perdata Islam … hlm. 120-121.
176 Ibid., hlm. 121.
- Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32
Tahun 1954.
Sedangkan Pasal 6 menjelaskan sebagai berikut:
- Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat
- Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban di sini menyangkut ghayah al- tasyri’ (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada Pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Apa makna tidak mempunyai kekuatan hukum ini? Sayang KHI tidak mempunyai penjelasan. Penulis lebih setuju jika tidak memiliki kekuatan hukum diterjemahkan dengan tidak sah (la yasihhu). Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.177 Sedangkan menurut Ahmad Rafiq, pencatatan perkawinan bukan menentukan sah tidaknya perkawinan. Pencatatan perkawinan hanyalah syarat administrtif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma
agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.178 Pandangan senada dikemukakan pula oleh Bagir Manan, bahwa
pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian. Jadi, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum.179
Pencatatan perkawinan dan akta nikahnya, merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Namun demikian tidak ada dasar hukum yang tegas dari al-Quran, yang menyuruh supaya ada pencatatan perkawinan dan aktanya. Tapi, bilamana ditelusuri ayat yang mengatur tentang muamalah, di mana setiap transaksi sangat dianjurkan supaya ada catatan yang jelas. Hal ini mengisyaratkan, bahwa setiap akad atau perjanjian – termasuk akad perkawinan–diperlukan adanya bukti autentik, dalam bentuk akta, guna untuk menjaga kepastian hukum. Ayat yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:
َٰيٓأَيُّهَا ٱلَِّينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إَِٰلٓ أَجَلٍ مُّسَمًّ فَٱكْتُبُوهُ…
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…
Berdasarkan ayat 282 dari surat al-Baqarah di atas, para ahli hukum Islam (fuqaha) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan perkawinan dan aktanya. Karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan bagi pasangan suami isteri. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqh yang berbunyi:
درؤالـمـفاسـد مـقـدم عـل جـلب الـمـصـالـح
Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.180
Dengan demikian, pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum guna mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban administrasi perkawinan secara umum di Negara Republik Indonesia ini.
Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat al-Quran yang berkaitan dengan mu’amalah (surat al-Baqarah ayat 282) dan maslahat mursalah dari perwujudan kemaslahatan.181
Di samping itu, pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama Islam, maupun menurut perundang- undangan.182
Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, sebagaimana yang diatur di dalam PP. No. 9/1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:
- Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU. No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan
- Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan
Pencatatan perkawinan merupakan proses dari awal sampai penandatanganan akta nikah oleh yang telah ditentukan dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Proses atau tata cara perkawinan ini disebut juga dengan syarat formil atau syarat adminstratif yang harus dipenuhi oleh setiap yang melangsungkan perkawinan.
Jadi, untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat materil dan syarat formil atau syarat administratif. Syarat formil adalah tata cara perkawinan mulai dari pranikah, ketika berlangsungnya akad nikah sampai selesainya akad nikah yakni penandatanganan akta nikah oleh kedua suami isteri, wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat perkawinan (PPN).
Akad nikah dilaksanakan bilamana syarat materiil dan formiil telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan akad nikah. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat formiil atau syarat administratif adalah tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan akad nikah serta setelah akad nikah dilaksanakan.
Syarat administratif ini bukanlah untuk menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi semata-mata bersifat administratif.183 Sedangkan soal “sah”-nya perkawinan Undang-Undang Perkawinan dengan tegas mengatakan pada Pasal 2 ayat (1), bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 183 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, … hlm. 17.
Syarat-syarat administratif ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1/1974 (PP No. 9/1975) adalah sebagai berikut:
- Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) PP. No. 9/1975 menetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKEC), hal ini berdasarkan ketentuan UU. No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang beragama non Islam, pemebritahuannya disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.
Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), sedangkan ayat (3) merupakan dispensasi bagi calon mempelai yang mempunyai urusan penting untuk tidak tunduk kepada Pasal 3 ayat (2) di atas. Dispensasi diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang lain. Pemberitahuan secara tertulis dapat juga dilakukan apabila karena sesuatu alasan pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh orang lain, orang tersebut harus ditunjuk dengan suatu kuasa khusus.184 Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 4 PP. No. 9/1975.
Dalam pemberitahuan tentang maksud untuk melangsungkan perkawinan tersebut, berdasarkan Pasal 5 PP.184 Ibid., hlm. 19.