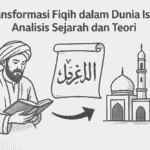(STRATEGY OF ISLAMIC WOMEN’S ORGANIZATIONS IN CLAIMING PUBLIC SPACES: A Study of A Muslimat NU and Aisyiyah )
Dian Rahmat Nugraha
Kankemenag Kota Tasikmalaya
Email : Kangdianrahmat@gmail.com
Abstrak |
| Keterwakilan politik perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, baik dari kebijakan afirmasi yang stagnan maupun resistensi ideologis berbasis penafsiran agama yang patriarkal, yang secara kolektif memperparah marginalisasi perempuan di berbagai sektor. Artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai strategi gerakan dua organisasi perempuan Islam terbesar, Aisyiyah dan Muslimat NU, dalam upaya mengatasi struktur marginalisasi dan meraih posisi strategis di ruang publik. Aisyiyah mengadopsi pendekatan Transformasi Teologis-Ideologis yang berfokus pada penafsiran ulang konsep khilafah perempuan dan mendorong politik praktis sebagai respons atas struktur yang menindas. Sementara itu, Muslimat NU menggunakan strategi Konsolidasi Kultural-Fungsional melalui pengembangan kapasitas kader dan advokasi Fiqh Responsif di tingkat grassroot. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua organisasi ini memiliki peran krusial sebagai agen perubahan struktural dengan memanfaatkan otoritas keagamaan untuk mendekonstruksi pemikiran gender yang bias, menjadikannya model bagi gerakan keadilan gender dalam konteks masyarakat Muslim. |
| Kata Kunci: Muslimat NU, Aisyiyah, Gender, Marginalisasi Perempuan, Nasaruddin Umar, Keadilan. |
1. Pendahuluan
Gerakan perempuan di Indonesia, meskipun memiliki akar sejarah yang kuat dan telah diperkuat oleh kebijakan afirmasi kuota 30% pasca-Reformasi, nyatanya masih menghadapi dilema struktural. Pencapaian posisi strategis perempuan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, masih jauh dari harapan. Dilema ini berpangkal pada dua sumber utama: pertama, kegagalan implementasi kebijakan afirmasi yang tidak disertai mekanisme sanksi yang kuat; dan kedua, resistensi ideologis yang bersumber dari penafsiran agama yang tekstual, kaku, dan cenderung patriarkal.
Faktor kedua, penafsiran agama yang bias gender, merupakan akar penyebab utama dari marginalisasi perempuan. Marginalisasi ini manifest dalam bentuk domestifikasi peran, subordinasi dalam pengambilan keputusan, dan minimnya akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik, yang dikuatkan melalui pembenaran teologis.
Artikel ini bertujuan menganalisis strategi yang diadopsi oleh dua organisasi perempuan Islam mainstream—Aisyiyah (Muhammadiyah) dan Muslimat NU (Nahdlatul Ulama)—dalam merespons tantangan ideologis yang mengakibatkan marginalisasi struktural. Penelitian ini berupaya membedah bagaimana Ormas keagamaan tersebut memanfaatkan otoritas dan modal sosial mereka untuk melakukan dekonstruksi pemikiran gender dan mendorong pencapaian posisi strategis kadernya.
2. Hasil dan Pembahasan
Aisyiyah dan Muslimat NU, sebagai organisasi dengan basis massa terbesar di Indonesia, memiliki kekuatan unik untuk memengaruhi narasi keagamaan dan sosial terkait gender. Meskipun memiliki manhaj (metodologi) keagamaan yang berbeda, keduanya sama-sama merumuskan strategi untuk menanggulangi marginalisasi perempuan dan mewujudkan keadilan gender.
2.1. Marginalisasi Perempuan dan Struktur Penindasan
Konsep marginalisasi perempuan (marginalization of women) merujuk pada proses pensubordinasian yang secara sistematis menempatkan perempuan pada posisi pinggiran dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih sering menjadi kelompok yang miskin waktu (time poverty), menanggung beban ganda (double burden), dan menjadi korban kekerasan. Dalam konteks Islam di Indonesia, marginalisasi ini seringkali dilegitimasi oleh:
- Tafsir Androcentris: Penafsiran kitab suci dan Hadis yang dilakukan oleh ulama laki-laki (atau ulama yang mengadopsi kacamata laki-laki) yang secara tidak sadar mengukuhkan superioritas maskulin.
- Sistem Patriarki Kultural: Struktur sosial-budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama (head of the household) dan membatasi mobilitas perempuan.
Untuk menghadapi struktur yang menindas ini, Teori Struktural Fungsional menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi melalui agen-agen yang mempromosikan fungsi adaptif baru dalam sistem. Dalam hal ini, Aisyiyah dan Muslimat NU berfungsi sebagai agen yang memperkenalkan fungsi-fungsi baru—seperti politik inklusif dan tafsir adil—ke dalam sistem sosial-keagamaan yang kaku.
2.2. Aisyiyah: Transformasi Teologis-Ideologis dan Fiqh Alternatif
Aisyiyah, dengan tradisi tajdid (pembaruan) yang diwarisi dari Muhammadiyah, memilih jalur Transformasi Teologis-Ideologis sebagai senjata utama melawan marginalisasi. Strategi ini menekankan bahwa masalah perempuan adalah masalah penafsiran, bukan masalah ajaran agama itu sendiri.
- Re-Interpretasi Konsep Khalifah: Aisyiyah secara eksplisit menafsirkan ulang bahwa perempuan memiliki peran mutlak sebagai khalifah fil ardh (pemimpin di bumi), setara dengan laki-laki. Penafsiran ini menghancurkan dasar teologis subordinasi. Menurut Teori Feminisme Islam, re-interpretasi semacam ini merupakan langkah penting untuk dekonstruksi wacana dominan dan membangun teologi yang membebaskan.
- Keterlibatan Politik Praktis: Dorongan Aisyiyah bagi perempuan untuk aktif di ranah politik dan publik merupakan implementasi dari peran khalifah. Keterlibatan ini bukan sekadar tokenism (simbolis), melainkan upaya strategis untuk memastikan suara perempuan diakomodasi dalam perumusan kebijakan, terutama yang bersentuhan dengan isu-isu marginalisasi seperti kekerasan domestik, hak-hak pekerja perempuan, dan pendidikan.
- Advokasi Fiqh Alternatif: Aisyiyah, melalui Majelis Tarjih, seringkali mengadvokasi pandangan hukum Islam (fiqh) yang lebih progresif, berani berbeda dengan pandangan jumhur (mayoritas ulama), jika pandangan tersebut dinilai lebih adil dan relevan dengan konteks kekinian (RO’FAH, 2005).
2.3. Muslimat NU: Konsolidasi Kultural-Fungsional dan Fiqh Responsif
Muslimat NU, yang kuat di akar rumput dan berbasis pada tradisi pesantren, memilih strategi Konsolidasi Kultural-Fungsional. Strategi ini fokus pada penguatan kapasitas kader dan advokasi hukum secara kolektif.
- Penguatan Karakter dan Kapabilitas: Tujuan Muslimat NU membentuk wanita Islam yang “bertaqwa, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab” adalah upaya fungsional untuk menciptakan kader yang memiliki kualitas esensial yang dibutuhkan untuk memegang peran publik. Ini adalah strategi jangka panjang untuk mengatasi marginalisasi karena ketidakcakapan atau kurangnya akses pendidikan.
- Pengembangan Fiqh Responsif dan Pandangan Ulama Reformis: Muslimat NU, melalui jaringan ulama perempuan dan Lembaga Bahtsul Masail, aktif dalam pengembangan Fiqh Responsif yang sensitif gender. Gerakan ini sejalan dengan pandangan Nasruddin Umar yang menekankan bahwa prinsip al-`adl (keadilan) harus menjadi kriteria utama (framework) dalam penafsiran. Umar (2005) menegaskan bahwa Islam melihat laki-laki dan perempuan setara sebagai hamba (’abd) dan khalifah; segala hukum yang lahir dari penafsiran yang tidak adil harus dikritik dan diubah. Muslimat NU menerapkan prinsip ini melalui ijtihad kolektif untuk menghasilkan panduan keagamaan yang memihak korban marginalisasi.
- Aksi Grassroot dan Layanan Sosial: Kekuatan Muslimat NU terletak pada jaringan layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan (PAUD/TK). Jaringan ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah marginalisasi di tingkat paling bawah, seperti kemiskinan, pendidikan anak, dan kekerasan domestik (KDRT), sehingga perubahan sosial bersifat terstruktur dan berkelanjutan.
3. Simpulan
Aisyiyah dan Muslimat NU adalah aktor kunci dalam upaya mengatasi marginalisasi perempuan di Indonesia. Keduanya membuktikan bahwa otoritas keagamaan dapat digunakan sebagai alat dekonstruksi terhadap tafsir patriarkal. Aisyiyah menggunakan pendekatan Transformasi Teologis-Ideologis, menekankan penafsiran ulang khilafah dan keterlibatan politik, yang didasari kerangka teoritis Feminisme Islam. Sementara itu, Muslimat NU mengandalkan Konsolidasi Kultural-Fungsional, fokus pada penguatan kapasitas individu dan Fiqh Responsif, dengan dukungan dari kritik pakar seperti Nasruddin Umar yang menuntut al-`adl sebagai inti syariat. Kedua strategi ini menunjukkan komitmen yang sama untuk mengubah posisi perempuan dari yang termarginalisasi menjadi agen perubahan yang setara dan strategis di ruang publik.
4.Daftar Pustaka
BPS, K. P. P. dan P. A. –. (2010). Kondisi Perempuan dan Anak di Indonesia 2010. BPS.
Chowdhury, N., Nelson, B. J., Carver, K. A., Johnson, N. J., & O’Loughlin, P. L. (1994). Women and Politics Worldwide. Yale University Press.
Dzuhayatin, S. R. (2009). Menakar “Kadar Politis” Aisyiyah. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 4(2).
Mursidah. (2013). Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah. MUWAZAH, 4(1), 87–103.
Ridjal, F., Margiani, L., & Husein, A. F. (1993). Dinamika gerakan perempuan di Indonesia. Tiara Wacana Yogya.
RO’FAH, M. (2005). The Indonesian Muslim women’s movement and the issue of polygamy: the ‘Aisyiyah interpretation of Qur’an 4: 3 and 4: 129. Approaches to the Qur’an in Contemporary Indonesia, 239–254.
Umar, N. (2005). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an. Paramadina.
Wahyudi. (2002). Sitti Walidah: Aktivis Perempuan dan Reformis Pendidikan. Dalam J. Burhanuddin (Ed.), Ulama Perempuan Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama.