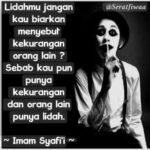Oleh :
KHAERUL UMAM, S.Ag*)
(Penghulu Ahli Madya KUA Pakuhaji)
A. MUQADIMAH
Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah ibadah yang memiliki nilai sakral dan diatur dengan aturan-aturan yang jelas dalam syariat. Salah satu rukun nikah yang wajib ada saat prosesi akad nikah adalah adanya kalimat ijab qabul. Ijab merupakan kalimat dari pihak wali pengantin perempuan yang menyatakan bahwa dirinya menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya kepada pengantin laki-laki. Sedangkan qabul merupakan jawaban menerima dari pengantin laki-laki atas ijab yang diucapkan oleh wali pengantin perempuan. Kalimat ijab qabul ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi inti dari akad nikah yang menunjukkan kesepakatan dan keabsahan hubungan suami istri. Kejelasan dan kesungguhan dalam mengucapkan kalimat ini adalah hal yang penting, karena menyangkut syarat sahnya sebuah pernikahan.
Di tengah masyarakat, umumnya shighat yang dipakai untuk ijab seorang wali atau wakilnya adalah: أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَان, shighat ini biasa diterjemahkan, “Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Fulanah binti Fulan…”, sementara qabul nikahnya biasa dipakai: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا لِنَفْسِيْ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ, di masyarakat, shighat ini diterjemahkan, “Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut..”. Sayangnya, shighat yang berlaku tersebut diragukan keabsahannya oleh sebagian kalangan. Alasannya karena ucapan wali/wakilnya “أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ” (Saya nikahkan dan kawinkan engkau) menurut pemahaman pihak ini mengesankan bahwa yang dinikahkan bukan mempelai wanita, tetapi mempelai pria, karena kata kerja أَنْكَحْتُ (Saya nikahkan) tertuju kepada dlamir mukhathab (mempelai pria), padahal menurut syariat yang dinikahkan adalah mempelai wanita.
Pihak tersebut menyatakan bahwa shighat ijab nikah yang benar mestinya, “Saudara Fulan, saya nikahkan denganmu Fulanah…” Demikian pula shighat penerimaan nikah oleh mempelai pria juga disangsikan keabsahannya. Argumennya adalah bahwa kalimat “Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah…” mengesankan perempuan menikahi laki-laki. Menurutnya, terjemahan qabul nikah yang tepat mestinya, “Saya terima menikahinya,” atau “Saya terima nikah dengan….” Shighat terakhir ini menurutnya dapat menjauhkan kesan bahwa perempuan menikahi laki-laki. Dari permasalahan tersebut muncullah pertanyaan, Benarkah anggapan itu? Apakah shighat yang lazim dipakai masyarakat mengakibatkan batalnya akad nikah? Maka tulisan ini akan mencoba menguraikan permasalahan shighat akad nikah tersebut.
B. PEMBAHASAN
- Pengertian Ijab Qabul
Kata ijab ( اوحبب-ييحبب-ايجاةبا ) dalam bahasa Arab mempunyai arti memberikan hak (Achmad Warson Munawwir, 1997:1537), maksudnya seseorang menyerahkan hak atas sesuatu terhadap orang lain. Sedangkan kata qabul ( كتل–يلتل–كتيلبا ) dalam Bahasa Arab mempunyai arti menerima, menyetujui, dan mengambil (Ibid :1087). Dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antarakeduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga.perasaan Ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat denganjelas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighat dalam pernikahan (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999:73).
Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak (wali pengantin wanita), yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun qabul merupakan pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab itu (calon mempelai laki-laki).k Ijab ialah perkataan wali calon pengantin wanita kepada calon pengantin laki-laki, misalnya kalimat zawwajtuka ibnatii…. (saya nikahkan kamu dengan putriku…). Sedangkan qabul adalah jawaban dari calon penganin laki-laki, misalnya saya terima nikahnya…. Jika sudah dilakukan ijab qabul dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki ata diumumkan, makanikahnya sah (Abdul Syukur Al-Azizi, 2015: 206).
Dalam pengucapan ijab qabul, tidak disyaratkan menggunakan kalimat tertentu. Tetapi, semua kalimat yang dikenal masyarakat sebagai ijab qabul dalam akad nikah, maka status nikahnya sah. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang tidak berbahasa arab, boleh melakukan akad nikah dengan bahasa kesehariannya. Akad nikah dikatakan sah, jika diucapkan perkataan yang menunjukan bahwah akad pernikahan itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh calon mempelai istri dan calon mempelai suami. Jadi, ketika melaksanakan ijab dan qabul wajib menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh orang-orang yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan, kemauan yang timbul dari kedua mempelai dan tidak dibolehkan menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mudah untuk dipahami artinya (Ibid : 74).
- Menjawab Keraguan Shighat Ijab Qobul yang lazim digunakan
Sesungguhnya, shighat nikah yaitu ijab qobul yang berlaku di masyarakat sudah sah secara fiqih dan tidak membatalkan pernikahan. Bahkan, shighat itu sudah bertahun-tahun dipakai dalam setiap akad pernikahan yang memakai bahasa Indonesia. Dan hampir tidak ada kiai atau ulama yang mengingkarinya. Seandainya keliru, tentu mereka sudah mengingatkannya. Yang pertama berkaitan dengan shighat ijab yang dipermasalahkan. Kejanggalan ini sesungguhnya bertentangan dengan tatanan bahasa atau gramatika Arab yang sudah masyhur dan dibakukan oleh para ulama.
Dalam ucapan ankahtuka wa zawwajtuka (saya nikahkan dan kawinkan engkau) terdapat kalimat fi’il ankahtu yang memiliki dua maf’ul (objek). Maf’ul pertama dlamir mukhathab “كَ (ka)” (engkau), yaitu mempelai pria. Maf’ul kedua adalah “Fulanah,” tepatnya nama mempelai wanita. Dalam tata bahasa Arab (nahwu), fi’il (kata kerja) yang memiliki dua maf’ul memiliki dua kondisi. Ada yang wajib mendahulukan salah satu maf’ul-nya, ada pula yang boleh menyebutkannya secara bebas, sehingga di antara dua maf’ul yang ada tidak disyaratkan tertib. Para ulama nahwu menjelaskan, kondisi yang wajib mendahulukan maf’ul terjadi bila terdapat keserupaan antara maf’ul yang secara makna berkedudukan sebagai subjek (fa’il filma’na) dengan maf’ul-nya. Contohnya seperti: أَعْطَيْتُ زَيْدًا عَمْرًا artinya, “Saya memberikan Zaid kepada ‘Amr.” Dalam kalimat di atas, Zaid memiliki kedudukan sebagai maf’ul (objek) dari dlamir mutakallim (aku), sekaligus menjadi subjek dari kata ‘Amr secara makna. Kemudian, ‘Amr juga berkedudukan sebagai objek dari dlamir mutakallim (aku) sekaligus subjek dari kata Zaid. Pemahaman kalimat di atas adalah Zaid sebagai pihak yang mengambil ‘Amr, yaitu objek yang diterimakan subjek kepada Zaid. Dalam contoh di atas tidak diperbolehkan mengakhirkan Zaid dari ‘Amr, sebab akan mengakibatkan ketidak jelasan antara pihak yang menerima dan objek yang diterimakan. Bila tidak ada keserupaan sebagaimana penjelasan di atas, maka boleh mengakhirkan atau mendahulukan di antara kedua maf’ul. Contohnya: أَعْطَيْتُ الثَّوْبَ زَيْدًا artinya, “Saya memberikan pakaian kepada Zaid.” Boleh juga dibalik: أَعْطَيْتُ زَيْدًا الثَّوْبَ artinya, “Saya memberi Zaid pakaian.” Dalam contoh ini, maf’ul yang berkedudukan sebagai subjek jelas dan bisa dibedakan dengan objek yang diterimakan. Zaid sebagai subjek penerima, sedangkan pakaian sebagai objek yang diterimakan kepadanya. (Lihat: al-Imam Ibnu ‘Aqil, Syarh Alfiyyah Ibni Malik, juz II, hal. 153).
Shighat ijab nikah yang berlaku di masyarakat selama ini, baik berbahasa Arab maupun terjemahannya, termasuk ke dalam penjelasan ini. Pakaian pada contoh di atas jelas menjadi objek yang diterimakan, sedangkan Zaid adalah penerimanya. Demikian halnya dalam shighat ijab nikah. Subjek penerimanya adalah mempelai pria, sedangkan objek yang diberikan kepada mempelai pria ialah mempelai wanita. Selain itu, sighat-nya juga bisa dibalik: أَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ إِيَّاكَ artinya, “Saya nikahkan dan kawinkan Fulanah dengan engkau.” Boleh pula diucapkan: أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ artinya, “Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Fulanah.”
Dalam bahasa Indonesia, kalimat “Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Fulanah,” dan terjemahan shighat ijab sebagaimana yang diusulkan, “Saudara Fulan, saya nikahkan denganmu Fulanah,” tidak memiliki perbedaan signifikan. Semua orang memahami bahwa shighat ijab memberi pengertian yang dinikahkan adalah perempuan, bukan laki-laki. Yang kedua adalah shighat qabul nikah qobiltu nikahaha wa tazwijaha (saya terima nikah dan kawinnya Fulanah). Shighat ini dijelaskan hampir seluruh literatur fiqih. Misalnya kitab Minhaj al-Thalibin atau kitab-kitab yang lain, hampir semuanya menyebutkan contoh shighat penerimaan nikah dengan kalimat tersebut. Redaksi qabiltu nikahaha (aku terima nikah dengan Fulanah) ditafsirkan oleh Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami dengan qabiltu inkahaha (aku menerima dinikahkan dengan Fulanah). Meskipun disampaikan dalam bentuk kalimat nikahaha, tetapi maknanya inkahaha, yaitu shighat mashdar dari ankaha-yunkihu-inkahan.
Syaikh Ibnu Hajar tidak mempermasalahkan contoh shighat qabul nikah yang disampaikan oleh Imam an-Nawawi dalam Matan Minhaj at-Thalibin tersebut, meski secara lahiriyah shighat qabiltu nikahaha terdapat kejanggalan, namun beliau tidak menyalahkannya, justru lebih memilih ta’wil (mengarahkan kepada pemahaman makna yang benar). Bahkan menurut riwayat Imam Al-Ajuri, redaksi nikahaha itu dipakai sebagai shighat qobul Sayyidina ‘Ali radliyallahu ‘anhu ketika menikahi Sayyidah Fatimah radliyallahu ‘anha. Disebutkan bahwa Sayyidina ‘Ali radliyallahu ‘anhu menyatakan qabul nikahnya dengan redaksi radlitu nikahaha (aku rida menikah dengan Fathimah).
Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami juga menegaskan:
(وَقَبُولٌ: بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُ أَوْ نَكَحْتُ أَوْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا) بِمَعْنَى إنْكَاحِهَا لِيُطَابِقَ الْإِيجَابَ وَلِاسْتِحَالَةِ مَعْنَى النِّكَاحِ هُنَا إذْ هُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَمَا مَرَّ وَرَوَى الْآجُرِّيُّ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْ عَلِيٍّ فِي نِكَاحِ فَاطِمَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – رَضِيت نِكَاحَهَا
Artinya, “Shighat qabul seperti ucapan suami “saya menikahi, atau saya terima nikahnya” dalam arti “menerima dinikahkan dengan mempelai perempuan.” Pemaknaan tersebut agar selaras dengan shighat ijab, juga karena tidak mungkin kata nikah ini diartikan dengan makna sesungguhnya. Sebab arti nikah adalah meliputi ijab dan qabul. Imam al-Ajuri meriwayatkan shighat qabul yang diucapkan Sayyidina ‘Ali radliyallahu ‘anhu adalah “saya rela menikahi Fatimah.” (Lihat: Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, juz 7, hal. 218).
Sementara itu dalam Lampiran Surat Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II/HM.01/2875/2015, Tanggal 9 November 2015 (yang menjadi pegangan PPN/Penghulu), shighat ijab qobulnya tidak jauh berbeda dengan yang lazim digunakan di Masyarakat: Lafaz ijab oleh wali: “Wahai Pulan bin Pulan, Saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya ………………..kepada engkau, dengan maskawin …………………tunai. Sedangkan lafaz qabul oleh calon uami: Saya terima nikahnya dan kawinnya ……………….binti …………….dengan maskawin tersebut tunai.
Dari referensi tersebut dapat kita pahami bahwa perbedaan kecil dalam redaksi penerimaan nikah tidak menjadi masalah. Demikian pula kesan-kesan yang dikhawatirkan dalam redaksi “saya terima menikahi Fulanah,” dapat ditepis dengan mengarahkan kalimat tersebut kepada pemaknaan yang benar. Sehingga terjemahan “saya terima nikah dan kawinnya Fulanah,” memberi pengertian “saya terima dinikahkan dengan Fulanah.” Jadi meski redaksinya memakai kalimat “nikah dan kawinnya Fulan,” namun yang dikehendaki adalah arti “dinikahkannya Fulanah oleh wali kepadaku.”
Demikian pula tidak ada perbedaan yang tajam antara shighat “saya terima nikah dan kawinnya Fulanah” dan redaksi qabul nikah yang diusulkan “saya terima untuk menikahinya/saya terima nikah dengan…” Sebab, semua kalimat itu memiliki maksud yang sama, yaitu menerima pernikahan mempelai wanita yang diserahkan oleh pihak wali. Argumen lain adalah semua bentuk shighat yang diucapkan dalam bahasa non-Arab, sepenuhnya disesuaikan dengan keumuman yang berlaku. Apa pun bentuk kalimatnya, sepanjang memiliki arti menikahkan dan menerima pernikahan, hukumnya sah.
Al-Imam as-Suyuthi menegaskan:
إنَّمَا يَتَجَاذَبُ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ فِي الْعَرَبِيِّ، أَمَّا الْأَعْجَمِيُّ فَيُعْتَبَر عُرْفُهُ قَطْعًا إذْ لَا وَضْعَ يُحْمَل عَلَيْهِ.
Artinya, “Tarik ulur antara makna asli dengan ‘urf hanya ada dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa non-Arab, yang dipertimbangkan adalah ‘urf menurut kesepakatan ulama, karena tidak ada makna asli yang menjadi tolak ukur.” (Lihat: al-Imam as-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, hal.95).
C. PENUTUP
Kalimat; “Saya menikahkan kamu kepada anakku…Saya menikahkan anakku kepada kamu..”, dalam struktur bahasa Arab keduanya adalah sama saja. Keduanya merupakan terjemah dari ankahtuka ibnati (أنکحتك ابنتی)..Saya menikahkan anakku kepada kamu…jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi أنکحت ابنتی إیاك karena bertentangan dengan متن ألفیة ابن مالك :
وفی اختیار لا یجٸ المنفصل # إذا تأتی أن یجٸ المتصل
Dalam kondisi normal tidak boleh menggunakan domir munfasil jika masih bisa (mudah) menggunakan domir muttasil. Dengan kata lain : Jika masih bisa أنکحتك ابنتی jangan أنکحت ابنتی إیاك, Jika masih bisa نعبدك jangan نعبد إباك , jangan terjebak oleh ” Bagaimana menterjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab karena kedua bahasa tersebut memiliki struktur yg sangat berbeda sekali.
Dalam pernikahan ijab kabul dilakukan oleh wali dan calon suami. Keduanya disebut pelaku ( فاعل ). Wali mengucapkan ijab : أنکحتك, Kata ت ( tu ) = فاعل لفظا ومعنی. Kata ت ( tu ) ini merujuk kepada wali. Kedudukannya sebagai فاعل ( subyek ) baik secara لفظ maupun معنی. Kata ك ( ka ) = مفعول به لفظا, Kata ك ( ka ) merujuk kepada calon suami. Kedudukannya sebagai مفعول به ( obyek ) secara لفظ, padahal dia adalah pelaku akad ( subyek ) atau فاعل secara معنی . Jadi ك ( ka ) yang merujuk kepada calon suami ini adalah مفعول به ( obyek ) secara لفظ tetapi sebenarnya ia adalah pelaku akad ( فاعل ). Inilah yang dimaksud dengan فاعل معنی.
Menterjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya dalam redaksi ijab kabul sebaiknya dihindari karena redaksi ijab kabul sudah melalui analisis yg kritis dan komfrehensif dari para ulama salaf ahli tata bahasa Arab. Artinya biarkanlah redaksi ijab kabul dalam bahasa Arab : أنکحتك وزوجتك……… قبلت نکاحها وتزویجها ……seperti apa adanya, jangan diutak-atik. Biarkan redaksi ijab kabul yg berbahasa Arab dijadikan standar baku layaknya meteran.Tetapi untuk menterjemahkan ke dalam bahasa yang lain baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa daerah dipersilakan dengan memperhatikan yuridis formal dan sosiologis religious, yang penting ada kata nikah atau kawin.
Walhasil dari permasalahan penggunaan shighat ijab qobul diatas, dapat disimpulkan bahwa ijab dan qabul nikah dengan terjemahan yang berlaku di masyarakat sesungguhnya tetap sah secara fiqih karena dua alasan. Pertama, shighat tersebut masih dapat diarahkan kepada pemaknaan yang benar. Kedua, yang menjadi standar untuk shighat berbahasa non-Arab adalah setiap kalimat yang lazim dipakai untuk memberi arti menikahkan dan menerima pernikahan, apa pun bentuk kalimatnya. Wallahu a’lam bisshawab.
REFERENSI
Achmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonsia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, 2008.
Abdul Syukur Al-Azizi, Buku Lengkap Fiqh Wanita,Yogyakarta: Diva Press, 2015.
Tihami dan Sohari Sahran, Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
Hasyim Asy‟ari, Dhau‟ Al-Misbah fi bayan Ahkam An-Nikah, Jombang: Pustaka Tebuireng 2019.
Lampiran Surat Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II/HM.01/2875/2015, Tanggal 9 November 2015
Syaikh al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, Juz 7.
Syaikh al-Imam as-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair.
Syaikh al-Imam Ibnu ‘Aqil, Syarh Alfiyyah Ibni Malik, Juz II.
————-
**)Penulis adalah Penghulu Ahli Madya pada KUA Pakuhaji Kab.Tangerang, Da’i/Penceramah,
penulis, dan pemerhati sosial keagamaan