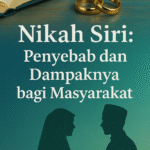Oleh : Khaerul Umam, S.Ag*)
A. PENDAHULUAN
Duuuuuaarrrrr…..kembali media sosial ramai dan dihebohkan oleh kasus perceraian yang diajukan sejumlah guru perempuan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat dan terima SK PPPK muncul di berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat hingga Banten. Berdasarkan laporan detik.com, sekitar 70% penggugat adalah guru perempuan yang menyatakan adanya ketimpangan ekonomi dengan suami. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang mencatat ada 50 orang guru yang mengajukan gugatan perceraian terhadap pasangannya. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. “Ada sekitar 50 orang,” kata Kepala Bidang Ketenagaan Dindikpora Pandeglang, Mukmin, kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
Hal serupa juga terjadi di Cianjur, puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan pendidikan Kabupaten Cianjur mengajukan cerai usai menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Gugatan cerai itu didominasi PPPK perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun detikJabar, dari 42 PPPK, sebanyak 30 orang baru mengajukan perceraian, sedangkan 12 orang lainnya sudah diproses dan tinggal menunggu dokumen perceraian ditandatangani oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur Ruhli mengatakan Pemicunya ekonomi. Salah satunya karena sekarang perempuannya sudah punya kemandirian ekonomi sebagai PPPK, sehingga menggugat cerai suaminya”.
Viralnya pemberitaan banyak terjadi kasus gugatan cerai yang dilakukan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat tersebut sontak menjadi sorotan masyarakat dan mereka menyayangkan kenapa hal itu terjadi. Pasalnya, setelah bertahun-tahun berjuang menembus ketatnya seleksi ASN/PPPK, kabar pengangkatan tentu menjadi momen yang membahagiakan. Status baru membawa harapan: gaji tetap, jaminan masa depan, dan pengakuan sosial. Namun, di balik stabilitas yang tampak itu, justru muncul ironi yang tak sedikit dialami oleh mereka yang baru menapaki tangga kemapanan: rumah tangga retak, gugatan cerai meningkat.
Dalam banyak kasus terjadi, suami tidak memiliki penghasilan tetap atau bekerja di sektor informal. Situasi ini diperparah oleh status baru istri sebagai pegawai pemerintah, yang sering kali menonjolkan disparitas ekonomi dengan pasangan. Pertanyaannya, apakah ketimpangan ekonomi atau kekurangan dalam hal nafkah dapat menjadi dasar kuat bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian? Bagaimana pandangan agama dan hukum positif di Indonesia menilai keabsahan alasan tersebut?
B. PEMBAHASAN
- Memahami konsep nafkah dalam pernikahan
Kata nafkah berasal dari kata (ََ أَنْفَق) dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: (َ نقص َو َقل) yang berarti “berkurang”. Juga berarti (فنىَوَذهة ) yang berarti “hilang atau pergi” (Amir Syarifuddin, 2007: 165). (النفقة) al-Nafaqah memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran” (Ahmad Warson Munawwir, 1997: 1449). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 1281).
Nafaqah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nafkah. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain (Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002: 136). Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.
Pengertian nafkah secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat fuqaha diantaranya Abdul Majid Mahmud Mathlub mendefenisikan nafkah yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh isteri, seperti; makanan, pakaian, perabotan, pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat (Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005 : 262). Sementara itu, Syaikh Hasan Ayyub mendefenisikan nafkah yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain (Syaikh Hasan Ayyub, 2001: 383). Dalam kitabnya Ahkamul Mar‟ati Fi Fiqhil Islamy, Imam Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi mendefenisikan nafkah yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu.
Nafkah merupakan elemen krusial dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakstabilan ekonomi semestinya tidak serta-merta menjadi alasan untuk bercerai, namun realitas menunjukkan bahwa kondisi finansial sangat memengaruhi keharmonisan keluarga. Dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada suami sebagai bentuk tanggung jawab utama dalam mengelola rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Ath-Thalaq ayat 7:
لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ٧
Artinya, “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS.Ath-Thalaq: 7).
Dalam ayat tersebut, Allah SWT mengisyaratkan bahwa kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan, tanpa memberatkan pihak suami. Dalam konteks ini, suami yang memiliki penghasilan lebih rendah dari istrinya seharusnya tidak serta-merta dijadikan alasan utama untuk mengajukan perceraian, selama ia tetap menunaikan tanggung jawab nafkahnya sesuai kemampuannya. Meskipun belum ideal menurut standar tertentu, pemenuhan kebutuhan pokok oleh suami tetap bernilai sebagai bentuk tanggung jawab.
Dalam dirkursus fiqih, ulama Imam Asy-Syarbini juga menjelaskan secara rinci batasan nafkah yang dapat dikatakan layak sesuai syariat:
قاَلَ النَّوَوِيِّ يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْكَسْبُ لِلإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يَلْزَمُهُ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ وَأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى تَكَسُّبِ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ لَزِمَهُ تَعَاطِيهِ، وَمَحَلُّهُ مَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى كَسْبٍ حَلالٍ. أَمَّا إذَا كَانَ الْكَسْبُ بِأَعْيَانٍ مُحَرَّمَةٍ كَبَيْعِ الْخَمْرِ أَوْ كَانَ الْفِعْلُ الْمُوَصِّلُ لِلْكَسْبِ مُحَرَّمًا كَكَسْبِ الْمُنَجِّمِ وَالْكَاهِنِ فَهُوَ كَالْعَدَمِ، (وَإِنْ خَالَفَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي) وَإِنَّمَا يُفْسَخُ (لِلزَّوْجَةِ النِّكَاحُ) بِعَجْزِهِ (أَيْ الزَّوْج) عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ حَاضِرَةٍ; لأَنَّ الضَّرَرَ يَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ، فَلَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ مُوسِرٍ أَوْ مُتَوَسِّطٍ لَمْ يَنْفَسِخْ; لأَنَّ نَفَقَتَهُ الآنَ نَفَقَةُ مُعْسِرٍ فَلا يَصِيرُ الزَّائِدُ دَيْنًا عَلَيْهِ، بِخِلافِ الْمُوسِرِ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ إذَا أَنْفَقَ مُدًّا فَإِنَّهَا لا تُفْسَخُ وَيَصِيرُ الْبَاقَّيْ دَيْنًا عَلَيْهِ
Artinya, “Imam an-Nawawi berkata: Wajib atas suami untuk bekerja (mencari nafkah) guna menafkahi istrinya, dan memang demikian hukumnya, sebagaimana ia juga wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dan apabila suami mampu bekerja untuk memperoleh nafkah standar orang kaya, maka wajib baginya untuk melakukannya. Namun, hal ini berlaku jika ia mampu bekerja dalam pekerjaan yang halal. Adapun jika cara memperoleh penghasilan tersebut melibatkan sesuatu yang haram secara zat, seperti menjual khamr (minuman keras), atau perbuatan yang mengantarkan kepada penghasilan itu haram, seperti penghasilan seorang peramal atau dukun, maka penghasilan seperti itu dianggap tidak ada nilainya (seperti tidak mampu bekerja). (Meskipun al-Mawardi dan ar-Ruyani berbeda pendapat dalam bagian yang kedua ini.) Adapun mengenai pembatalan akad nikah (fasakh) diperbolehkan jika suami tidak mampu memberikan nafkah minimal seorang yang tidak mampu (mu’sir) dan ia tinggal bersamanya (hadir), karena dalam kondisi itu kerugian (dharar) benar-benar nyata bagi istri. Namun jika suami tidak mampu memberikan nafkah standar orang kaya atau menengah, maka tidak dapat dibatalkan. Berbeda halnya jika yang memberi nafkah adalah seorang suami kaya atau menengah namun hanya memberikan sedikit (seperti satu mudd saja), maka akad nikah tidak dibatalkan, namun kekurangan dari nafkah tersebut tetap menjadi utang atasnya.” (Al-Khathib Asy-Syirbini, Mughnil Muhtaj, [Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, t.t.], jilid V, halaman 178).
Kewajiban memberikan nafkah juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami sesuai dengan penghasilannya, wajib menanggung: (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan anak. Bahkan di ayat (6) Pasal 80 KHI dinyatakan isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b, (Ahmad Rofiq, 1997: 186-187). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut bahwa suami wajib menafkahi keluarga dan istri bisa menggugat cerai jika tidak diberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan sah. Ditambah dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 bahwa bukti tidak bekerja tetap atau penghasilan tidak cukup dapat memperkuat alasan gugatan.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama suami masih giat berusaha memenuhi kebutuhan keluarga melalui pekerjaan yang halal, meskipun di sektor informal, maka ia tetap dinilai menjalankan kewajiban nafkahnya. Islam tidak mensyaratkan nafkah harus berasal dari pekerjaan formal atau penghasilan tinggi, melainkan dari usaha yang sungguh-sungguh dan layak sesuai kemampuan. Karena itu, istri yang mendapati suaminya tetap berjuang secara konsisten dalam menafkahi keluarga hendaknya mempertahankan ikatan pernikahan dan tidak menjadikan keterbatasan materi sebagai alasan utama untuk bercerai, kecuali ada faktor lain yang menjadikan percerai satu-satunya solusi dan jalan keluar dari problem rumah tangga
2. Memahami tujuan pernikahan
Tujuan pernikahan atau perkawinan adalah salah satu asas dari 6 (enam) asas atau prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara KHI Pasal 2 dan 3 menyatakan; “Perkawinan menurut hukum Islam Adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Pasal 2), “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaadah dan Rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang)” (Pasal 3).
Dari kedua regulasi rumusan tujuan perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena itu, suami isteri harus saling melengkapi dan saling membantu setiap kekurangan masing-masing pihak. Disamping itu faktor ajaran Islam adalah unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia, sebab ajaran Islam memberikan petunjuk antara yang baik dengan yang buruk, bagaimana sikap jiwa sewaktu mendapat nikmat dan ketika mendapat musibah. Dari dalam rumah tangga yang selalu dihiasi dengan ajaran-ajaran agama akan memantulkan sinar bahagia, ketenangan, kenikmatan rohaniyah, walaupun dalam situasi kekurangan, kemiskinan dan kesulitan. Unsur kedua rumah tangga bahagia ialah terciptanya hubungan harmonis antara sesama keluarga, antara suami isteri, antara anak-anak, antara anak dan ibu bapaknya dan dengan yang lainnya (Bidang Urais, 2022: 51-52).
Dalam rumah tangga bahagia, senantisa tergalang pergaulan yang harmonis antara sesama keluarga. Semuanya menempatkan diri laksana awak kapal yang sedang mengarung samudera luas dan penuh gelombang, masing-masing dari sejak kapten atau nahkoda sampai mualim dan penjaga mesin, kelasi dan tukang masak menjalankan tugas masing-masing dengan gembira dan tanggung jawab demi keselamatan bersama. Unsur berikutnya dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia adalah hemat dan hidup sederhana. Sebagian besar kehancuran rumah tangga karena keroyalan hidup. Tidak berhemat dan tidak memikirkan hari esok, tidak mengerti ada musim hujan dan musim panas. Hawa nafsu ingin hidup mewah akan tetapi tidak seimbang dengan sumber pendapatan yang ada, sehingga timbullah satu keadaan yang gawat di rumah tangga itu, besar pasak daripada tiang.
Selanjutnya menyadari cacat diri sendiri, banyak orang yang terlalu rajin melihat cacat orang lain tetapi jarang sekali melihat cacatnya sendiri. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Apabila setiap pemimpin rumah tangga menyadari sepenuhnya, maka dapat dihindarkan perasaan benar sendiri (Bidang Urais, 2022: 54-55).
3. Memahami Hak dan Kewajiban Suami Isteri
Tujuan perkawinan yang sangat mulia di atas tidak akan terwujud apabila pasangan suami isteri tersebut tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila pasangan suami istri tersebut sudah mengetahui peran dan fungsinya masing-masing serta memahami apa hak dan kewajibannya, maka dambaan bahtera rumah tangga yang Bahagia, kekal dan penuh cinta kasih akan terwujud.
Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur di dalam Bab IV Pasal 30-34, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan Masyarakat”. Sementara KHI Pasal 77 ayat (1) berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan Masyarakat” (Ahmad Rofiq, 1997: 183).
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 79 ayat (2) menyatakan: “Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam Masyarakat”. Selanjutnya pada Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 77 ayat (2) menyatakan: “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan dapat memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya tercantum pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban memberikan nafkah juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami sesuai dengan penghasilannya, wajib menanggung: (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan anak.
Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana tercantum pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 77 ayat (5).
4. Meningkatkan komunikasi dan harmonisasi relasi dalam keluarga
Fenomena meningkatnya angka perceraian pasca pengangkatan ASN/PPPK mulai mencuat di berbagai daerah. Banyak pasangan yang bertahan dalam keterbatasan, justru berpisah setelah mencapai kehidupan yang dianggap mapan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara sederhana: mengapa stabilitas ekonomi tidak sejalan dengan stabilitas emosional dan relasi?
Dalam logika umum, kemapanan seharusnya memperkuat rumah tangga. Namun, kehidupan manusia tidak berjalan linier. Saat status sosial berubah, cara pandang seseorang terhadap dirinya dan pasangannya pun ikut berubah. Dalam banyak kasus, pengangkatan sebagai ASN/PPPK membawa perubahan identitas yang cukup drastis: dari “yang berjuang” menjadi “yang berhasil”, dari “yang menggantungkan” menjadi “yang merasa mandiri”. Perubahan ini tidak selalu disadari. Namun dalam relasi, ia hadir dalam bentuk ketimpangan baru. Pasangan yang dulu berjalan beriringan, kini merasa berada di jalur yang berbeda. Waktu, perhatian, dan energi yang dulu diprioritaskan untuk keluarga, mulai terbagi ke dalam urusan dinas, pelatihan, pergaulan baru, dan tuntutan profesionalisme.
Fenomena ini juga berkaitan erat dengan dinamika makna dalam hidup. Setelah kebutuhan ekonomi terpenuhi, manusia kerap mencari makna yang lebih dalam. Namun, jika makna itu tidak ditemukan dalam relasi, maka pasangan bisa merasa kosong, tidak nyambung, bahkan tak lagi tahu untuk apa mereka tetap bersama. Inilah yang kerap menjadi penyebab “perceraian senyap”, tanpa konflik besar, tapi dilandasi rasa keterasingan yang makin membesar. Ketimpangan ritme hidup juga ikut memperlebar jarak. Salah satu pasangan mulai hidup dalam dunia yang lebih sistematis—penuh aturan dan target. Sementara yang lain masih berada dalam dunia hidup yang lama. Perbedaan ini menciptakan semacam “dunia dalam dunia” yang tak mudah dijembatani jika tidak ada komunikasi yang reflektif.
Selain itu, masyarakat kita masih menempatkan ASN/PPPK sebagai simbol keberhasilan. Ini sering kali membentuk ego baru dalam diri seseorang. Mereka merasa lebih dihargai, lebih mampu, bahkan kadang merasa tak lagi membutuhkan pasangan secara emosional maupun finansial. Dalam kondisi ini, relasi mudah tergelincir menjadi relasi kuasa, bukan lagi relasi kesetaraan.
Gugatan cerai yang muncul tidak melulu karena pertengkaran. Justru banyak yang muncul karena rasa sepi yang lama dipendam. Bahasa cinta berubah menjadi bahasa administratif. Kehangatan yang dulu mengikat, kini digantikan oleh rutinitas dan peran sosial yang kaku. Hubungan kehilangan napasnya. Kemapanan, pada akhirnya, bukan jaminan bagi keharmonisan. Ia justru menuntut kedewasaan baru, baik secara pribadi maupun sebagai pasangan. Tanpa pembaruan makna dan komunikasi, kemapanan bisa menjadi ruang hampa yang membunuh keintiman. Rumah tangga yang dulu tumbuh dari perjuangan bersama, bisa runtuh karena kehilangan arah di tengah pencapaian.
C. PENUTUP
Media sosial kembali ramai dan dihebohkan oleh viralnya berita kasus perceraian yang diajukan sejumlah guru perempuan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat dan terima SK PPPK muncul di berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat hingga Banten, yang berdasarkan laporan detik.com, sekitar 70% penggugat adalah guru perempuan yang menyatakan adanya ketimpangan ekonomi dengan suami. Kabar ini sontak menjadi sorotan masyarakat dan mereka menyayangkan kenapa hal itu terjadi, sungguh ironis memang selama ini banyak pasangan yang mampu bertahan dalam keterbatasan, justru berpisah setelah mencapai kehidupan yang dianggap mapan
Berdasarkan berbagai penjelasan diatas baik yang dikemukakan oleh para ulama dan regulasi tentang perkawinan, dapat disimpulkan bahwa selama suami masih giat berusaha memenuhi kebutuhan keluarga melalui pekerjaan yang halal, meskipun di sektor informal, maka ia tetap dinilai menjalankan kewajiban nafkahnya. Islam tidak mensyaratkan nafkah harus berasal dari pekerjaan formal atau penghasilan tinggi, melainkan dari usaha yang sungguh-sungguh dan layak sesuai kemampuan. Karena itu, istri yang mendapati suaminya tetap berjuang secara konsisten dalam menafkahi keluarga hendaknya mempertahankan ikatan pernikahan dan tidak menjadikan keterbatasan materi sebagai alasan utama untuk bercerai, kecuali ada faktor lain yang menjadikan percerai satu-satunya solusi dan jalan keluar dari problem rumah tangga.
Seorang istri hendaknya melakukan sejumlah pertimbangan matang sebelum mengajukan gugatan cerai semata-mata karena ketidakpastian pendapatan suami. Di antara pertimbangan penting tersebut adalah menilai kelayakan nafkah yang diberikan suami, bukan berdasarkan gaya hidup, tetapi pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pokok sesuai dengan standar hidup yang wajar: apakah dalam kategori mampu, menengah, atau sederhana. Memperhatikan ada tidaknya mudarat atau kerugian yang bersifat berkelanjutan bagi keluarga akibat ketidakstabilan ekonomi tersebut. Menekankan pada esensi tanggung jawab: mampu atau tidaknya suami menunaikan kewajiban nafkah, bukan sekadar stabil atau tidaknya pendapatan, ataupun apakah ia bekerja di sektor formal atau informal.
Dalam posisi ganda sebagai ASN/PPPK atau pendidik di sekolah dan ibu rumah tangga, penting bagi seorang istri untuk menimbang kembali secara bijak sebelum mengambil keputusan besar seperti perceraian. Jika para istri yang baru diangkat menjadi pegawai tetap berniat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka langkah tersebut harus melalui proses hukum, termasuk pengujian terhadap klaim gugatan dan mekanisme mediasi untuk mencari jalan damai. Selain itu, status sebagai aparatur negara juga menuntut kepatuhan pada prosedur formal, termasuk mendapatkan izin dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, para istri juga perlu merefleksikan kembali aspek emosional dan sosial dari perjalanan karier mereka; bahwa pencapaian sebagai pegawai tetap tidak terlepas dari dukungan lingkungan dan keluarga, termasuk pasangan. Isteri perlu merenung ulang perjalanan kisah kasih mereka sebelum menikah dan mengayuh bersama bahtera rumah tangganya mulai dari nol, susah senang dilalui bersama, segala kesulitan dan cobaan di awal berumah tangga dihadapi dan diatasi bersama, jangan hanya karena status sosial berubah maka cara pandang terhadap dirinya dan pasangannya pun ikut berubah, merasa tak lagi membutuhkan pasangan secara emosional maupun finansial. Ingatlah, dengan diangkatnya isteri menjadi seorang ASN/PPPK itu merupakan bagian rizqi dari Allah SWT karena ditakdirkan berpasangan dengan seorang lelaki yang kini menjadi suaminya, dan kemungkinan besar juga keberhasilan isteri dalam mencapai karirnya tidak lepas ikut andilnya suami dalam setiap do’a di keheningan malamnya serta do’a di setiap sujud di raka’at terakhir shalatnya. Ingatlah, jangan sampai menyia-nyiakan orang-orang yang selama ini setia menemani perjalanan hidup kita, jangan seperti peribahasa ini, “Habis manis sepah dibuang atau Ada uang abang disayang, tak ada uang abang kutendang”.
Dalam konteks ini, negara dan lembaga kepegawaian tidak bisa hanya mempersiapkan pegawai dari sisi teknis dan administratif. Pendidikan karakter dan penguatan relasi juga menjadi penting. Karena relasi yang sehat adalah fondasi dari integritas seorang ASN/PPPK. Bagi pasangan yang sedang atau baru saja meraih kemapanan status sosial, penting untuk memahami bahwa perubahan status sosial perlu diimbangi dengan kematangan emosional. Tujuan hidup bersama perlu diperbarui, bukan dibiarkan usang. Jika tidak, kemapanan bisa menjadi awal dari keterasingan—dan keterasingan yang dibiarkan, bisa berubah menjadi perpisahan. Wallahu a’lam bishshawab.