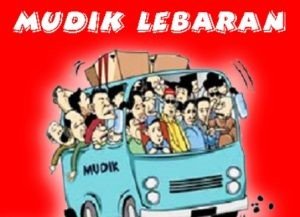C. PENUTUP
Fenomena mudik lebaran di Indonesia memang unik dan jarang ditemukan di negara lain. Sekitar satu minggu sebelum lebaran, para perantau berbondong-bondong meninggalkan ibukota dan kembali ke kampung halaman. Mudik Lebaran merupakan suatu tradisi untuk berkumpul lagi bersama keluarga dalam suasana perayaan hari raya Iedul Fitri atau Lebaran, mereka saling mengunjungi dan berkumpul untuk silaturahmi dan saling mema’afkan yang kemudian terkenal dengan tradisi Halal bihalal. Selain tiga dimensi mudik diatas (Spiritual, kultural dan psikologis), mudik pada hakikatnya merupakan ajang untuk menyemai kesalehan vertikal dan horizontal. Kesalehan vertikal bermakna bahwa orang-orang yang merayakan harus kembali pada kefitrian (kesucian) jati diri kemanusiannya sebagai hamba Tuhan setelah berpuasa selama bulan Ramadhan. Kemudian kesalehan horizontal bermakna bahwa orang-orang harus menyambungkan tali silaturahim dengan keluarga, sahabat, dan kerabat tanpa adanya keinginan untuk menunjukkan prestise, melainkan murni untuk menjalin kekeluargaan dan kehangatan kembali.
Silaturrahmi dan Saling memaafkan adalah bagian dari ajaran Islam dan sangat diperintahkan oleh agama kita serta sebagai upaya kita dalam menjaga, mempertahankan dan mensyiarkan nilai-nilai ajaran agama kita, yang dalam Maqashid al-Syari’ah disebut dengan menjaga agama (Hifdzu al-Diin). secara sosiologis para pemudik adalah aktor sosial yang membangun sistem sosialnya sendiri dan menjadi bagian dari berputarnya roda perekonomian negara, yang dalam Maqashid al-Syari’ah disebut dengan menjaga harta (Hifdzu al-Maal). Seperti pihak swasta, mereka juga terimbas oleh sistem sosial pemudik ini. Beragam perusahaan transportasi mendapatkan keuntungan besar ketika jaman mudik. Pemilik P.O Bus, travel, kereta, pesawat, kapal laut, semua mendapatkan limpahan berkah dari aktivitas pemudik ini. Para pemudik ini juga berpotensi akan mengalirkan sumberdaya yang dimilikinya di tempat tujuan. Pengeluaran ini bisa berupa kebutuhan rutin, sampai kepada kegiatan berbagi kepada saudara dan tetangga. Sumberdaya yang besar ini pasti memiliki dampak ekonomi dan sosial di daerah tujuan.
Jika dilihat dari perspektif kesejahteraan sosial, mudik sebenarnya memiliki dampak bagi kesejahteraan sosial. Masyarakat yang mudik atau pulang kampung bisa dengan beragam alasan dan bisa dalam waktu yang temporer atau permanen. Mudik bisa berkaitan dengan masalah urbanisasi, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masalah kemiskinan di pedesaan dan bertambahnya tenaga kerja dari desa yang memenuhi wilayah perkotaan telah menciptakan urbanisasi yang tak terkendali. Banyak warga dari desa yang ingin bekerja di perkotaan karena tergiur dengan iming-iming kehidupan kota yang lebih baik daripada di desa. Padahal mencari pekerjaan di perkotaan tidak lebih mudah dibandingkan mencari pekerjaan di pedesaan. Secara lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan di kota memang lebih banyak dan lebih beragam. Namun bagi orang-orang yang tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan yang rendah, dan akses informasi yang terbatas, mereka justru akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan di kota. Alhasil mereka akhirnya memilih bekerja di sektor informal yang tidak memiliki kepastian pendapatan dan tidak mendapatkan perlindungan.
Urbanisasi yang tidak terkendali akan menimbulkan kantung-kantung pemukiman kumuh di perkotaan. Munculnya pemukiman kumuh merupakan dampak ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan infrastruktur dasar, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang biasanya bekerja di sektor informal. Infrastruktur dasar itu meliputi akses terhadap layanan penyediaan air minum, sanitasi, sistem pengelolaan air limbah dan persampahan hingga drainase pemukiman Akhirnya, harapan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dengan hidup di perkotaan justru tidak tercapai. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah seyogianya untuk terus membangun daerah-daerahnya dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan di daerah terutama daerah pedesaan sehingga pemerataan kesejahteraan bias terwujud dan arus urbanisasi bisa diminimalisir. (Disarikan dari berbagai sumber).
——
**) Penulis adalah Penghulu Ahli Madya pada KUA Kec. Pakuhaji Kab.Tangerang, Da’i/Penceramah, penulis, dan pemerhati sosial keagamaan.